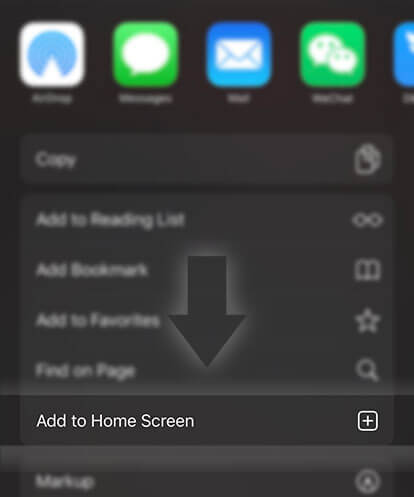《BRAINWASH》28. SEHANGAT ARUNIKA
Advertisement
Sesampainya di kafe dekat kampus, aku memesan minuman cokelat panas dan air putih. Selera makanku sudah hilang, ditambah perut yang enggak juga protes meski belum diisi nasi. Padahal aroma makanan menguar dan sudah mengusik hidung sejak aku membuka pintu Kafe. Setelah menunggu 45 menit, Erlangga akhirnya datang. Wajahnya menyiratkan rasa menyesal Karena sudah membuatku menunggu lama.
“Mai, sorry lama. Kamu sudah makan?” Tanya Erlangga sembari duduk di depanku.
“Belum. Aku enggak lapar.”
“Tapi kamu tetep harus makan, Mai.”
Tiba-tiba saja air mataku kembali tumpah. Erlangga tetap duduk dalam diam. Dia memberiku ruang untuk menangis sampai puas. Setelah tangisku surut, baru kumulai menceritakan apa yang terjadi di rumah.
“Aku pergi dari rumah, Ngga. Papa tadi nampar aku.” Bulir-bulir kembali memenuhi pulupuk mata, aku pun menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Mencoba menahan air mata agar enggak tumpah lagi.
Erlangga enggak juga mengeluarkan pendapatnya. Hanya menarik napas panjang.
“Aku enggak ngerti, Ngga. Rasanya aku udah enggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Rasanya semua sikapku jadi salah semua di hadapan Papa.”
Aku diam sejenak, “Aku habis bikin rumah berantakan sampai mamanya Evalia enggak pulang tiga hari. Aku lakukan itu demi kaluargaku kembali utuh. Heran deh aku sama Papa, kok bisa-bisanya masih aja belain mamanya Evalia. Udah jelas-jelas dia pelakor yang bikin keluarga hancur.”
“Mai, kamu boleh sedih, nangis berjam-jam juga boleh. Tapi kamu harus tetep makan. Kamu harus sehat, enggak boleh sakit. Aku pesankan nasi goreng, ya?” tawar Erlangga.
Mendengar Erlangga menyebut nasi goreng, mengingatkanku akan menu makan malam yang kubuat tadi. Menu yang kubuat dengan tulus dan sepenuh hati hati untuk Papa dan Evalia berakhir di meja makan tanpa disentuh. Aku yakin, sampai saat ini pun pasti enggak ada yang menyentuh nasi goreng itu.
“Mai? Aku pesankan, ya?” tanya Erlangga hati-hati, meski begitu tetap saja membuatku terkesiap dari lamunan.
“Emm, enggak usah Ngga. Aku lagi enggak ingin nasi goreng,” tolakku. Sepertinya sampai beberapa bulan aku enggak akan bisa makan nasi goreng. Menu yang harus aku coret dari daftar makan kalau enggak ingin sakit hati.
“Mi? Burger?” Erlangga kembali menawarkan.
Advertisement
“Burger aja,” jawabku singkat.
Erlangga segera menghampiri Pramusaji yang baru saja meninggalkan dua meja di sampingku. Setelah itu dia kembali duduk di depanku dan menanyakan apa yang aku perlukan sekarang. Pandangannya jatuh pada ransel di kursi sebelahku.
“Aku butuh tempat menginap untuk semalam ini saja. Besok temani aku mencari indekos dekat kampus, ya.”
Erlangga terlihat sedang berpikir. Sampai pesananku datang pun dia masih terlihat berpikir dan sibuk dengan ponselnya. Aku jadi merasa enggak enak hati karena sudah merepotkan.
Setelah perutku terasa kenyang, Erlangga mengajakku keluar kafe. Dia enggak bilang apa-apa sebelumnya sampai kami tiba di sebuah rumah berpagar hitam dan bertembik putih.
“Ini rumah kakakku. Masuk, yuk.”
Erlangga berteriak mengucap salam. Kutepuk bahunya memberitahu bahwa ada bel di sana. Belum menekan bel, si pemilik rumah keluar. Seorang wanita berusia sekitar pertengahan tiga puluhan berjalan melewati teras menuju pagar.
“Kebiasaan! Itu kan ada bel. Berisik tahu, ganggu tetangga aja,” protes pemilik rumah kepada Erlangga.
“Ayo, masuk, yuk, masuk,” ajak Kakak Erlangga kepadaku.
Dia ramah sekali, meski tinggi badannya enggak setinggi Erlangga tapi wajah mereka mirip bagai kembar. Perbedaan hanya pada bentuk rahang saja. Bila rahang Erlangga terkesan kokoh dan agak lebar, khas lelaki. Rahang kakaknya lebih ramping sehingga bentuk dagunya pun meruncing.
“Jadi gimana ini gimana?” tanya Kakak Erlangga sambil mengulurkan tangan mempersilakanku duduk. “Eh kenalan dulu. Aku Arun, Arunika. Mbaknya Erlangga.”
Kujabat tangan Mbak Arun, “Maira.”
“Oke, Erlangga jelasin coba. Pusing aku baca pesan Whatsapp-mu tadi.”
Jadi saat di kafe tadi, Erlangga sudah memberitahu tentangku kepada Mbak Arun. Tapi sepertinya cuma sekilas saja, makanya Mbak Arun menanyakan lagi. Karena aku sedang butuh tempat untuk tidur semalam, terpaksa kuceritakan dengan sejujurnya. Mbak Arun yang awalnya menolak, akhirnya mau menerima dengan syarat.
“Kamu izin dulu sama orang tuamu. Baru boleh menginap di sini,” kata Mbak Arun sebelum meninggalkanku di ruang tamu diikuti Erlangga yang mengekor.
Syarat dari Mbak Arun susah-susah gampang sebenarnya. Aku bisa saja bilang ke Mama kalau menginap di rumah teman. Namun, bila Mama menanyakan alasanku, aku jawab apa? Aku belum ingin menceritakan mengenai tamparan Papa di pipiku tetapi aku juga enggak mau berbohong kepada Mama. Aargh! Benar-benar bikin pusing. Aku mulai memikirkan kata-kata yang tepat agar diizinkan Mama tidur di rumah Mbak Arun. Saat itulah tiba-tiba Erlangga menghampiri.
Advertisement
“Sudah? Izin mamamu aja kalau enggak mau izin papamu,” saran Erlangga.
“Aku bingung bilangnya,” keluhku.
“Ribet juga kamu ini. Bilang aja menginap di rumah teman. Kalau mamamu tanya lebih lanjut, baru cerita sejujurnya. Kalau enggak tanya, ya sudah, kamu enggak perlu jelasin kalau emang enggak mau jelasin.”
Segera kukirim pesan WhatsApp ke Mama. Singkat saja, enggak sampai sepuluh kata dan enggak menjelaskan apa pun. Bukannya membalas pesan, Mama malah meneleponku. Aku jelas makin bingung. Erlangga menyuruhku menerima telepon dan berkata sejujurnya. Otakku benar-benar sedang buntu saat ini. Jadi semua perkataan Erlangga aku turuti.
“Assalamualaikum, Mama.”
“Walaikumsalam. Kok mendadak? Lagi ngerjain tugas sampai harus begadang ya?” tanya Mama perhatian.
Kutarik napas panjang sejenak sebelum menjawab. “Ma, sebenarnya aku habis ribut sama Evalia. Papa ....” Aku sengaja enggak melanjutkan perkataanku. Semakin aku mengingat dan mengatakan atas tamparan yang Papa lakukan, membuatku makin sedih dan putus asa. Membuatku semakin merasa enggak dicintai Papa.
“Sudah Mama duga akan begini jadinya. Ya sudah, kamu di sana saja dulu. Besok kita pikirkan lagi gimana selanjutnya. Ah, biar Mama aja yang mikir. Kamu fokus sama tugasmu. Oke, Sayang?”
Aku menghela napas lega. “Makasih Mama.” Ku tutup telepon setelah mengucap salam.
“Yes!” seruku pelan.
Erlangga melempar senyum padaku lalu berjalan memanggil Mbak Arun. Enggak lama Mbak Arun datang sambil membawa nampan berisi tiga cangkir beraroma teh melati yang sangat menenangkan pikiran. Asap tipis menari-nari di atas cangkir porselen berwarna putih polos tanpa hiasan.
“Sudah dapat izin?” tanya Mbak Arun ramah.
“Sudah. Mamaku barusan menelepon juga,” jawabku sambil tersenyum.
“Wah bagus, tuh. Ayo diminum tehnya. Erlangga, setelah tehmu habis langsung pulang, ya. Cewek-cewek cantik mau tidur,” usir Mbak Arun dengan halus.
“Kalau gitu, pelan-pelan aja habisin tehnya, sampai pukul sebelas lah ya,” sahut Erlangga cuek.
“Aku lempar sapu kalau setengah jam lagi teh-mu belum habis.” Ancaman Mbak Arun membuatku dan Erlangga terbahak.
Setelah Erlangga pulang karena diusir dan diancam Mbak Arun, aku membantu membawa nampan berisi cangkir-cangkir kosong ke dapur. Jam di dinding memang sudah menunjukkan pukul 22.30 jadi wajar bila Mbak Arun mengusir adiknya itu.
Rumah Mbak Arun enggak seberapa besar. Hanya terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, kamar mandi, mushala kecil, ruang TV yang berhubungan langsung dengan ruang makan dan dapur. Meski begitu, rumahnya bersih dan nyaman sekali. Ada satu keanehan yang enggan aku tanyakan. Enggak ada satu barang pun yang berhubungan dengan anak kecil. Apa Mbak Arun belum punya anak ya? Besok aja aku tanyakan ke Erlangga.
“Taruh di meja makan sini aja, Mai,” kata Mbak Arun sambil beranjak duduk di kursi makan. Di hadapannya ada laptop yang terbuka.
“Mau tidur sekarang? Kamar kamu yang di sini, ya.” Mbak Arun menunjuk kamar nomor dua yang ada di belakangnya.
“Emm, iya Mbak.”
“Enggak usah nungguin aku. Aku biasanya tidur lewat tengah malam.”
Mbak Arun tipe orang yang gampang akrab. Banyak yang dia ceritakan tentang keluarga dan dirinya padahal baru kali ini loh kita ketemu. Dari Mbak Arun, aku jadi tahu kalau Erlangga itu bungsu dari tujuh bersaudara. Anak pertama bukan saudara kandung, melainkan anak saudara ayah yang dijadikan pancingan karena sudah tiga tahun menikah namun orang tua Erlangga belum punya anak juga.
“Aku anak pertama itu, Mai. Usiaku 37 tahun dan belum punya anak. Banyak omongan, banyak saran, banyak cacian ... Ah! Banyak deh pokoknya. Tapi semua itu enggak pernah aku bikin pusing. Kalau aku sih yang penting keluarga, ya. Hubunganku sama keluarga harus baik. Alhamdulillah hubunganku sama orang tua dan adik-adik angkatku baik, sama orang tua dan saudara kandung juga baik. Itu yang penting.”
Mbak Arun bilang kalau banyak kepala itu banyak masalah. Banyak saudara, banyak juga bertengkarnya. Pertengkaran-pertengkaran kecil yang membuat mereka makin akrab. Ada satu ucapan Mbak Arun yang membuatku berpikir sampai susah tidur.
Kata Mbak Arun, “Kita enggak pernah bisa minta akan lahir di rahimnya siapa. Akan gimana jalan hidup kita. Yang bisa kita lakuin ya cuma nerima aja, gitu. Terus berusaha jadi orang yang baik.”
Advertisement
- In Serial766 Chapters

Never Judge
“Y-y-you’re the heir of Reyes Group?” Ian managed to stutter out.
8 1252 - In Serial50 Chapters

Wedding In Pandemic ( Completed ✔)
Weddings are always special. But when it is your cousin's wedding it is even more. Maya is a sweet independent girl, who radiates happiness and energy everwhere she goes. It is her cousin sisters wedding and she is nothing less than ecstatic about it. But things take a turn when the prime minister of india announces the 1st stage of lockdown on the evening of the engagement party. Both bride's and groom's family are stuck together and cant leave until the lockdown lifts. It is an almost bearable situation until Maya sees the groom's brother. The blast from the past hits her smack across the face as the brother is the last person she expected to see here. Its none other than Adhitya sankar, the person who broke her heart 6 years ago. What happened in Adhi and Maya's life that made them each other's nemesis? What happens when 2 south indian familys who barely know each other are stuck together for weeks?Fate is a bitch who likes to play games. When lovers turned enemies meet will sparks fly or will it explode on their faces?Read on find out. #1 on general fiction#1 on lockdown #1 on college romance#1 in first-time #1 on forced proximity#4 on Arranged marriageCover by : @gj_sankar
8 137 - In Serial67 Chapters

Blind By Love
"This is Rumaan's child" I heard mama said. I didn't look up at her. I keep my head lowered. because I didn't have the courage to face her."This is not my child," he said abruptly.I looked at him with wide eyes. I was beyond shocked. What he just said.Did I hear him right? No, he can't say that. How can he?But as he looked away from me, my heart beats stopped. my breath hitched.And that's where he broke me completely"HOW DARE YOU RUMAAM" mama yelled and slapped him."Mama..." he was shocked that his mother slapped him" don't call me mama.," she yelledand was about to hit him again but I stopped her"no mama," I said and they all turned to me I slowly get up and went in front of them" he's right.. this is not his child" I put my hand on my stomach and said I had tears in my eyes but I did not let them fall in front of him whom I loved with my everything because now I was tired of crying for his love. I was blind. Blind by love but not anymore.Everyone looked at me shocked even Rumaan couldn't believe what I just said★★★Hana Rafeeq Mirza a beautiful innocent kind-hearted 20 years old girl Everyone loves cared and respect her but the one she loves since childhood her cousin her love of life, didn't love her neither he respects her.Rumaan Ahmed Mirza a hot handsome and flirt 23 years old boy. He was famous as a playboy in America.He never cared for those things which he gets easily and that's what Hana whom he got so easily. And he just wanted to get rid of her at any cost.He knew that Hana was crazy for him that's why he always took her advantage.Will Rumaan ever realize his mistakes or if he realised it will be too late???Want to know?? Yes? Then join their journey with meWarning: this is my first story and English is not my mother tongue. so it maybe has a lot of grammar mistakes. So read it at your own riskStarted: 26/1/2020Finished:16/6/2020#1 in heartbreak#4 in betrayal #3 in spiritual#1 in innocent#1 in spiritual
8 123 - In Serial6 Chapters

TVPWTLGH
◡̈ 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞. the villainous princess wants to live in a gingerbread house. ⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆ღ 𝐬𝐲𝐧𝐨𝐩𝐬𝐢𝐬. I knew I had reincarnated as a child from a poor and ruined home.And yet, I thought about the pastry shop, which in my previous life, I could not afford.But in this life everything is different.Originally, I was a possessed young woman who got in the way of the protagonist's love story and ultimately wanted power.If I want to avoid the bad ending, I must show the biggest lack of interest in power. Then, I will be able to bake the sweets that I have always wanted so much.But with the emperor, not everything is so simple..."How long will you avoid me for?"The Crown Prince who is the male lead who eventually drove me to ruin..."You are my only cousin."The Duke, the strongest knight of the empire..."I love your lime pie."Even a slave who is meant to plunge a knife into me..."I want to save you from death."Do you want me to be by your side?악역 황녀님은 과자집에서 살고 싶어요⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆disclaimer: this is NOT my novel, this is only a fan translation, all rights to the author and please try to support the official works if you can!꒰ translated by mio (@mioscorner) ꒱
8 197 - In Serial79 Chapters

Misery✓
{Slowly Editing}❝𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚊 𝚌𝚒𝚐𝚊𝚛𝚎𝚝𝚝𝚎, 𝚒𝚝'𝚜 𝚏𝚞𝚗 𝚊𝚝 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚋𝚞𝚝 𝚎𝚟𝚎𝚗𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚒𝚝 𝚔𝚒𝚕𝚕𝚜 𝚢𝚘𝚞❞♣♣♣So the person who abused her thinks they will get away with this. Oh I am gonna fucking kill them. Fade, the name sounds so similar but who is she? But what was happening to me? I never did something like this for anyone so why her? Did I just fucking like her? She looked so naive, she doesn't deserve this at all.♣♣♣Fade Emerson, a simple girl. She is pure as ice and one of the sweetest souls anyone can meet. Abused and treated like a servant, she has no hope left. Stefan Marcus, the CEO. The typical bad boy, rude, womanizer, toxic and cold. He is who she meets. Somewhere in between they already had met before. Will her life stay the same or will they both find true love? *Warning* This has sexual abuse, torture, foul language and mentions of self harm. Please be advised.Cover by me.
8 160 - In Serial33 Chapters

Stay [taekook FF]
When jungkook an introvert son of a single mom meets a reckless son of a mafia leader, the heartthrober Kim taehyung.....what would happen when the troublesome son of the mafia grow intrested in a innocent sweet boy like jungkook ??What would happen when taehyung finds out that the sweet innocent boy is hiding pain behind that pretty smile?A little preview : ---------------------------------------°•°•°•°•°Jungkook smiled and looked ahead."Thanks for trusting me ...."------°•°•°•°•°•°•°------"I asked something and don't even think of running away I won't let you go until you tell me what the fuck is going on!" ------°•°•°•°•°•°•°------"Tae.....can you.....kiss me...?" ----------------------------------------°•°•°•°•°This is a taekook fanfiction .! Contents !Rom-comMafia aucontents : boyXboy top: Tae bottom: Kookfluff : a little!⚠️ Warning ⚠️! angst 😈😈Attempted [email protected]Self harmsmut : average ( ͡° ͜ʖ ͡°)Violence/ action Mature languageThis is a mafia fanfiction so there will be possible deaths of characters so if anyone has a problem with it, I recommend not to read this English is my third language and also this is my first time writing so please ignore the mistakes ...(╥﹏╥) Started: 29 June 2021Finished: 14 September 2022Book no :- #1All rights reserved ©️yeontanismybias
8 161




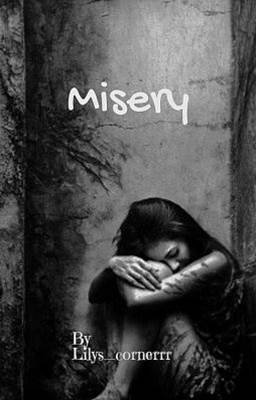


 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl