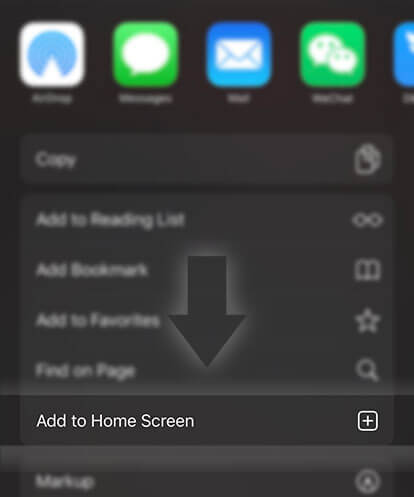《BRAINWASH》19. HOPE
Advertisement
Sejak kejadian bentrok dengan pembacanya Evalia, aku enggak pernah lagi mau berurusan dengan dunia literasinya. Sumpah. Ngeri banget menghadapi fans garis kerasnya Evalia. Belum lagi kata-kata kasar. Terlebih saat malam harinya, Evalia bercerita tentang akun yang membulinya. Dia membuat postingan di sosial medianya, menceritakan kalau ada akun yang menghina tulisannya. Dengan kata-kata bijak dan mengatasnamakan kesehatan mentalnya, ia secara halus mencari dukungan dari pembacanya untuk menghabisi akun yang menghina tulisannya. Pantas saja jika akunku tiba-tiba diserang oleh Evalicious.
Aku enggak habis pikir, kenapa ada saja orang-orang yang mau saja diperalat untuk menyerang orang lain, sampai berkata-kata kasar. Sebenarnya, aku enggak masalah dengan fans Evalia yang menegur kelakuanku dengan cara yang baik-baik. Apa yang kulakukan memang salah, tapi bukan berarti mereka boleh mencaci maki dengan kata-kata kasar yang enggak pantas, kan?
Oke, kita lupakan soal Evalia dan fans garangnya. Pagi ini setelah dibuat kapok, alu mengubah strategi. Aku kembali mendekati Papa dan menyita perhatiannya. Bukankah yang ingin kurebut kembali adalah papa? Jadi, mari fokus saja pada papa.
"Pa, Maira hari ini bareng sama papa, ya," pintaku dengan tatapan penuh harap.
Setelah menelan nasi uduk buatan mama Ambar, papa bertanya, "loh, tumben. Kamu enggak bareng sama Erlangga?"
Aku mengerucutkan bibir. "Aku, kan, anak papa. Masa disurih nebeng sama orang mulu, sih," keluhku dengan nada paling merana yang kubisa.
Papa tertawa sambil mencubit gemas pipiku. "Bisa aja kamu Mai," kata papa. "Evalia, kamu enggak keberatan berangkat bareng mama, kan?" tanya Papa.
"It's not big deal, Pa," sahut Evalia dengan ibu jari ke atas.
Yes! Berhasil. Aku bakal menyita waktu papa kali ini.
"Ngomong-ngomong, Mai, kamu belum ngebalin Erlangga secara resmi, loh, ke kita," kata papa dengan nada santai.
Aku tersedak nasi kuning. Serius, rasanya enggak enak. Hidungku sampai pedih dan mataku sampai berkaca-kaca. Evalia membantu menepuk-nepuk punggungku, sedang mama Ambar langsung menyodorkan segelas air putih ke arahku. Hebat banget mereka berdua, acting-nya ngalahin Galgadot, deh.
"Resmi apanya, sih, Pa," elakku setelah berhasil menghentikan batuk. "Kita cuma teman, kok," imbuhku lagi.
"Loh, papa, kan, enggak bilang kalian bukan teman. Papa cuma nanya kenapa Erlangga enggam pernah di ajak masuk dan dikenalin ke papa, mama Ambar dan Evalia. Apa jangan-jangan kalian memng lebih dari teman?" goda papa tanpa mau membiarkanku mengelak dari topik ini.
Advertisement
Kuteguk sekali lagi air di dalam gelas gingga tandas. "Nanti Maira kenalin, kok," sahutku berharap dengan begitu papa mau berhenti menanyaiku.
"Kapan?" desak papa lagi yang sepertinya enggak mau kalah.
Nanti, Pa. Nanti kalau papa sudah balik lagi ke mama. Aku enggak mau mengenalkan Erlangga ke mama Ambar apalagi Evalia. Aku enggak mau Erlangga sampai tahu betapa bobroknya kehidupan pribadiku. Aku merasa minder dengan latar belakang keluarganya. Erlangga dibesarkan di keluarga yang utuh dan harmonis. Bukan keluarga berantakan dan pelakor yang merusak kebahagiaan seperti yang kumiliki sekarang.
"Soon," jawabku yang lebih seperti doa. Doa agar semua tujuanku lekas tercapai.
Seperti kataku tadi, aku akan menyita waktu papa hari ini. Aku meminta papa kembali menjemputku sepulang kerja. Sebenarnya hari ini kuliahku berakhir sejak jam tiga sore, tapi demi bisa mendapatkan perhatian papa, aku rela menunggu tiga jam di kampus.
Setelah masuk ke dalam mobil, aku meminta papa menemaniku memilih kado ulang tahun untuk eyang uti. Aku senang karena papa enggak menolak ataupun menunjukan tanda-tanda keengganannya. Kami memilih pusat perbelanjaan di bilangan Laksda Adisucipto. Selesai membeli kado, aku mengajak papa makan malam di salah satu restauran di dalam mall itu juga.
Kugunakan kesempatan ini untuk mengadu pada papa. "Aku sedih banget, Pa," kataku membuka obrolan.
Papa meletakkan kembali garpu dan pisau dagingnya. "Sedih kenapa?" tanya papa.
Kuhela nafas dan membuatnya sedramatis mungkin. Kalau Evalia saja bisa mencari simpati dari pembacanya, aku juga harus bisa mendapatkan simpati papa. "Sebenarnya waktu laptop Evalia rusak, mama Ambar nuduh aku yang ngerusakinnya hanya karena aku ada di rumah sebelum kalian pulang. Padahal hari itu aku pulang cepat karena enggak ebak badan. Sanpai di rumah pun aku langsung tidur di kamar. Kenapa ya, kok, mama Ambar tega banget nudih aku begitu? Apa karena aku bukan anaknya?"
Kali ini bulir bening menggelayut di bulu mataku. Aku enggak berpura-pura ketika bulir bening nyaris meluncur keluar. Harusnya pertanyaan ini kuajukan sejak bertahun-tahun lalu. Seharusnya sudah sejak dulu ketika mereka memperlakukanku enggak adil, kuajukan pertanyaan ini.
Papa meraih tangan kananku ke dalam genggamannya. "Mai, papa yakin Mama Ambar tulus sayang sama kamu. Dia menyayangi kamu sama seperti dia menyayangi Evalia. Papa yakin betul kalau mama Ambar enggak pernah bermaksid menuduh kamu." Apa tersenyum untuk menenangkan perasaanku.
Advertisement
Jujur saja itu enggak membantu sama sekali. Hatiku malah semakim teriris pilu. Papa selalu membela mama Ambar dan Evalia. Apa papa juga pernah membelaku seperti itu? Apa papa akan terus ada di pihakku seperti itu? Aku enggak yakin. Selama ini saja papa lebih memilih mengorbankan perasaanku.
"Kenapa kamu enggak coba membuka hati untuk belajar menerima mama Ambar dan Evalia? Papa tahu ini bukan hal mudah, begitupun bagi mereka. Bukan hal mudah menerima kehadiran kamu, tapi mereka berhasil, kan? Bagaimana kalau sekarang giliran kamu yanv belajar menerima keberadaan mereka?"
Tuh, kan, apa kubilang. Papa hanya peduli dengan perasaan mama Ambar dan Evalia. Papa enggak pernah mau memikirkan bagaimana perasaanku. Papa enggak pernah mau sedikit saja peka sama hatiku.
Aku diam enggak menyahut, bukan karena aku setuju dengan papa. Aku hanya enggak ingin terluka malam ini. Jadi, kubiarkan saja percakapan itu mengambang di udara. Berharap suatu saat papa bisa memahamiku.
Di jalan pulang, aku melakukan panggilan video pada mama. Sayang, mama enggak menerimanya. Namun, mama melakukan panggilan balik. Enggak apa-apa, deh, meski bukan panggilan video.
"Hai, ma. Lagi apa?" tanyaku begitu suara mama menyapa.
"Masih di kantor, Nak. Ada apa?" Suara mama terdengar singkat-singkat khas ketika dia enggak pengin diganggu olehku.
"Uhmmmm, enggak ada apa-apa, sih. Maira cuma mau cerita aja kalau tadi aku habis belanja kado buat eyang uti. Iya, kan, Pa?" tanyaku pada papa sebagai isyarat pada mama kalau aku sedang bersama papa.
Berhasil. Suara mama mendadak menjadi ramah dan menyenangkan. "Kamu beli apa untuk eyang uti?" tanya Mama yang tiba-tiba saja jadi tertarik dengan isi kadoku.
"Peralatan menyulam, Ma. Kata Eyang Kung, belakangan ini eyang uti hobi senang menyulam lagi, Ma. Ehh, mama enggak keberatan, kan, kalau aku loudspeaker?"
"Kenapa harus keberatan, sih, Sayang," kata mama dengan nada lembut yang hampir enggak pernah lagi kudengar.
Segera kutekan gambar speaker di layar ponsel. "Papa tadi bantuin aku pilih kadonya, loh, Ma," kataku mengumumkan bantuan papa tadi.
"Ohh, ya?" tanya mama dengan suara yang mengalun merdu. "Terima kasoh, loh, Gun, udah mau diperotin sama Maira," kata mama yang jelas bukan untukku.
"Bukan apa-apa, kok, Nil. Maira, kan, juga anakku," sahut papa.
Diam-diam aku menyembunyikan senyum melihat papa kembali mengobrol ringan dengan mama.
"Kamu enggak dibikin pusing, kan, sama Maira? Dia itu kalau milih barang suka lama banget. Bikin pegel orang yang nemeninnya," ujar mama lagi yang diakhiri dengan tawa kecil.
"Ya, samalah kayak kamu gitu," sahut papa kemudian tertawa bersama mama.
Kubiarkan papa berbincang dengan mama. Meski enggak lama, tapi interaksi mereka membuatku bahagia. Aku jadi membayangkan kalau yang ada di rumah adalah mama dan kami masih menjadi keluarga utuh yang bahagia.
Sebelum keluar dari mobil kukatakan pada papa, "terima kasih buat hari ini, Pa. Maira seneng banget malam ini."
Papa tersenyum lebar kemudian mengusap puncak kepalaku. "Sama-sama, Mai," sahut papa, kemudian merapikan barang-barangnya.
"Pa," panggilku menahan papa yang sudah akan membuka pintu mobil. "Maira kangen pergi bertiga seperti dulu." Sebentar ku gigit bibir bawahku, kemudian melanjutkan kalimat yang sengaja kujeda tadi. "Dulu, meskipun papa sudah pisah sama mama, tapi kita masoh sering pergi bertiga. Maira kangen kayak gitu lagi."
Papa menatapku dalam. Sorot matanya sulit untuk kuartikan. Setelah lama ditelan sunyi, akhirnya papa menjawab, "kita bisa ketemu mamamu bareng-bareng dengan mama Ambar dan Evalia juga."
Setelah mendengar jawaban papa, kubiarkan lelaki yang di dalam darahku mengalir darahnya itu meninggalkan mobil. Aku bersyukur pada lampu taman yang temaram. Dengan begitu aku bisa menyembunyikan mataku yang mulai pedih menahan sesak. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamarku.
Harusnya malam ini menjadi malam yang bahagia. Kenapa, sih, kebahagiaanku yang sedikit ini masoh harus dirusak oleh mama Ambar dan Evalia?
1356
💜💜💜
Advertisement
- In Serial24 Chapters

Devils Spawn
I never wanted the life of a biker, so being shipped off to live with an uncle who is the president of one of the most feared biker gangs in the country wasn't something I was looking forward to. I didn't think when I moved that I would learn to love the life they offer or that I would fall in love with a biker. I never thought for a second that the things to come would test me. This is the story of my love, my loss, and the shit I have to deal with living with these idiots!Interested in my life yet??
8 226 - In Serial17 Chapters

satoru gojou x reader | Wanted for pleasure | Jujutsu Kaisen
[ COMPLETED ]You came to Tokyo from NYC to teach and learn more about jujutsu techniques. With an iq of 213 but you aren't very athletic. Satoru Gojou was someone you find annoying. slowly, you grew used to his presence. Your high iq couldn't figure out why you were so attached to him...NOTICE: I DO NOT own any of the characters. I made the cover.Wait is it Satoru gojou or gojo.. cuz I use gojou
8 106 - In Serial6 Chapters

The Song of Souls
WARNING TO MY USUAL READERS: This is not my usual style of story. I've decided to turn this into an anthology of short one-shot stories, that are very atypical of my usual stories or style. Some will be horror, others romance, and others just stupid silly ideas I have. Basically, a collection of shorts I write when I need a break from my usual writing style. I'll include a summary at the start of each "chapter" telling you what to expect. MAKE SURE YOU READ THE SUMMARY! The content and quality of each story will probably vary wildly. (One is even a horror romance featuring an eldritch horror. I promise it's weirder than it sounds.) If you do want to check out my usual writing, be sure to take a gander at my ongoing series, Of Men and Dragons. It's a bit of a long haul at this point, but hopefully it's worth the read! Cover: By Gej302
8 65 - In Serial53 Chapters

The Unwanted Proposal
(Highest rank #3 in romance on 15/02/2017, #5 in romance on 13/11/16)Note: the story is unedited and you might find many mistakes.Avni is a beautiful independent lady of 25 whose life is almost perfect. But soon that is going to change when under certain circumstances she is bound to marry Aditya, her father's best friend's son. Aditya is handsome and rich. He is a man of secrets. What happens when they have to live under the same roof.
8 175 - In Serial169 Chapters

Quotes
A book of my favorite quotes. I don't own any of these, obviously.
8 333 - In Serial17 Chapters

Twilight Jacob X Male Oc Book One
Bella Swan has a twin brother Valentine Swan who just so happens to be mate of Jacob Black. While unknown danger lurks in the dark, Valentine's unknown powers keeps growing, and apparently a war centuries ago between the beings of the dark may just so happens to answer at least some questions.Book one is completely done, but if you want to read it in all one huge chapter. There's 17k words you can see that on my page titled book one of Twilight Jacob x male oc(Things to note; this is a modern remake of Twilight /2022/ and also vampires burn, but don't worry most of them have daylight rings, necklaces or bracelets also imprinting is the equivalent of a mate.)
8 181







 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl