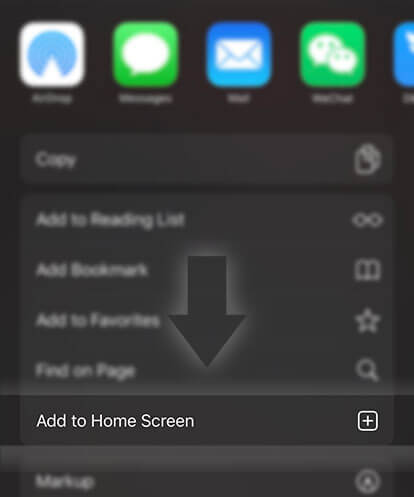《UTARI》Bab 11 - Jawaban Sebuah Pertanyaan
Advertisement
HARI itu banyak sekali berita yang datang ke telinga Utari mengenai orang-orang terdekatnya. Selain itu, beberapa hari ini, Utari bermimpi tentang profesor gila yang menggunakan anaknya sendiri sebagai kelinci percobaan penelitiannya. Ya, cerita Pak Jay tentang anak angkatnya itu memang cukup terekam jelas di kepala Utari.
Lamunan Utari buyar saat ponselnya bergetar. Pagi itu tidak seperti biasanya, ibu menelepon dari rumah.
"Halo... ada apa, bu?"
"Ibu tadi baru dapat kabar kalau adikmu, Ratri positif hamil."
"Alhamdulillaah... Nanti aku telepon Ratri untuk mengucapkan selamat kalau begitu, bu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ya, pak."
"Ya, sama ibu juga menunggu kamu mengenalkan calonmu ya."
Wajah Utari yang semula merekah, langsung layu seketika. Mengapa harus terselip pernyataan itu di tengah pembicaraan tentang kehamilan Ratri.
"Oh, iya... Maya, istrinya Seno juga sudah hamil katanya."
"Oh ya? Alhamdulillaah.."
"Utari, ibu ini kok ya makin lama maki khawatir sama kamu. Ratri dan Maya sudah hamil. Larasati minta kawin. Kamu mau ketinggalan kereta?"
"Aduh, bu. Daritadi kenapa ujung-ujungnya ke aku sih."
"Ndak apa. Ibu cuma mau mengingatkan, mumpung masih bisa mengingatkan. Bapak baru sadar kalau kalian itu seumuran. Kamu ini kan perempuan, Seno yang lelaki saja sudah mau puna anak."
"Ya... doakan saja Utari segera ketemu jodoh, bu."
"Ya, nduk. Cari Abimanyu-mu dengan segera ya. Ndak usah terlalu lama. Kasihan adik kamu Laras yang ingin menikah dengan Ridwan. Ibu juga tidak setuju kalau kamu sampai dilangkahi lagi. Ya sudah... Selamat bekerja ya, nduk."
Sepanjang percakapan tadi sampai bapak menutup teleponnya, Utari tidak berhenti merasa terheran-heran. Mengapa ibu bisa-bisanya menasihatinya lewat telepon begitu. Tapi, setidaknya ibu membawa kabar bahagia.
Ia senang sekali saat tahu Ratri hamil. Adiknya itu sudah menunggu-nunggu kedatangan si jabang bayi selama setahun lebih. Ia tidak pernah terlihat mengeluh, tapi suatu waktu Utari melihatnya menangis sendirian karena meratapi penantiannya yang dirasanya begitu lama untuk mendapatkan seorang anak. Lalu, ia menghubungi Ratri untuk memberinya selamat.
"Mbak, cepat lah cari calon suami. Biar nanti kalau anakku lahir, dia sudah punya pak de." Begitu kata Ratri di ujung percakapan mereka.
Pagi itu membuat Utari tersadar bahwa ia waktu telah berlalu begitu cepat. Tak heran bila orang-orang disekitarnya memintanya untuk berlari lebih cepat, menggapai masa depan, dan mungkin juga merelakan masa lalu.
Semenjak kejadian Sirene mencuri dengan pembicaraanya dengan Azalea, Utari selalu mengajak temannya itu untuk makan di luar kantor. Siang itu, mereka makan di kedai soto kalkun tak jauh dari kantor. Utari menceritakan kepada Azalea bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya pagi itu. Ia juga bercerita soal lelaki yang ditemuinya di dalam bus menuju kantor dan ia ingat dengan satu-satunya mantan kekasih yang dimilikinya, Abimanyu. Kemudian soal mawar merah yang diberikan oleh Pak Jay dan cerita Sirene. Seperti biasa, Azalea selalu jadi pendengar yang baik. Menanggapi cerita-cerita Utari dengan tulus sehingga ia tidak enggan menumpahkan hampir segalanya kepada Azalea.
Namun, ada terasa berbeda ketika Utari menceritakan tentang berita kehamilan adiknya dan rencana pernikahan sepupunya. Azalea terlihat muram, lantas Utari menjadi merasa bersalah karena ia tidak sadar apa yang diceritakannya barusan menyinggung perasaan Azalea.
Telunjuk kanan Azalea mengetuk-ngetuk meja saat Utari menceritakan tentang kehamilan Ratri. Tingkahnya seperti sedang mau ujian komprehensif, tegang. Lalu, Azalea membuka kacamatanya dan Utari dapat melihat kalau Azalea sedang tidak sakit mata. Mata sebelah kanannya lebam kebiruan. Seseorang telah melukai perempuan di depannya yang terlihat sekali sedang berusaha terlihat tegar.
"Siapa yang melakukannya, Za?" Sebenarnya Utari sudah menebaknya.
Azalea memakai kacamata hitamnya lagi. Air mata meluncur dari balik kacamata itu. "Aku tahu Utari bagaimana perasaan adikmu. Aku juga bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika adikmu mengetahui kalau dirinya sedang mengandung. Pasti rasanya sangat menyenangkan, sangat melegakan."
Advertisement
"Johan tidak pernah melakukan ini sebelumnya, Utari. Barangkali rasa kesal dan menyesalnya sudah menumpuk. Baru kemarin ia bisa melampiaskan segalanya kepadaku. Aku tahu ia kecewa karena aku belum juga dapat mewujudkan keinginannya menjadi seorang ayah. Tetapi, kemarin aku baru benar-benar paham bagaimana kekecewaan yang ia rasakan. Aku mencium bau alkohol dari mulutnya—baru sekali itu aku mendapatinya mabuk." Azalea menyeka air matanya lagi.
"Aza, kamu tidak menceritakan ini ke orang tua kamu?"
"Tidak, Utari. Aku pikir ini masalah keluargaku—dengan suamiku. Aku memang takut saat ia tiba-tiba memukul wajahku. Tapi, rupanya ada ketakutan yang lebih besar yang aku rasakan, Utari."
"Apa? Apa itu, Azalea?"
"Aku takut terlalu dalam mengecewakannya. Rasa takut kehilangan seseorang yang sangat kau cintai. Aku baru benar-benar merasakannya sekarang. Tapi, ia menenangkanku tadi pagi. Ia meminta maaf, mencium kening, dan punggung kakiku. Aku tahu saat itu kalau Johan juga mencintaiku. Tapi, entah kenapa aku tetap takut."
Utari mendekati Azalea, lalu menawarkannya sebuah pelukan. Azalea membiarkan tubuhnya didekap lembut oleh Utari yang ingin membuatnya merasa aman. "Bukankah Tuhan selalu memberikan kejutan di waktu yang tidak kita duga-duga, Azalea." Kata Utari pada Azalea, sembari memaknai apa yang diucapkannya barusan ke dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta bukanlah hal yang mudah dipadamkan, tidak dengan jarak, bahkan tidak pula dengan kekerasan. Bayangan Abimanyu tiba-tiba muncul. Lalu, ia berharap laki-laki itu akan menjadi salah satu kejutan yang sedang disimpan Tuhan untuk dirinya dan akan ditunjukkan-Nya suatu hari nanti. Terlalu pahit, tapi Utari harus mengamini situasi ini. Bahwa ternyata ia masih menyimpan rindu yang mengundang pilu, yang juga berarti cinta.
UTARI mendapatkan undangan via email dari Bu Ribka untuk hadir di Rumah Harapan pada Hari Sabtu minggu depan. Di email itu, Bu Ribka menambahkan catatan kalau itu adalah pertemuan rahasia, tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang secara personal mendapatkan undangan itu. Oleh karenanya, Utari tidak memberitahu Aksara tentang rencananya pergi ke Rumah Harapan pada hari sabtu.
Dua minggu kemudian, Utari pergi ke Rumah Harapan seorang diri. Saat ia sampai kesana, suasana begitu sepi. Ternyata, yang diundang dalam pertemuan itu hanya Utari dan Ibu Michelle.
"Sebenarnya ada apa sih, bu?" Tanya Utari. Bu Michelle mengangguk, menyetujui pertanyaan Utari.
"Nanti kalian juga tahu. Kita tunggu seorang lagi, ya."
"Jadi, yang diundang tiga orang?" Tanya Bu Michelle.
"Ya. Tetapi, anggota yang diundang hanya kalian berdua. Orang yang satunya lagi bukan anggota di sini. Tapi, dia dulu teman saya saat masih sekolah dan baru bertemu lagi—sudah banyak berubah memang. Kami bercerita banyak, hingga saya menceritakan tentang Rumah Harapan ini kepadanya."
"Lalu?" Tanya Utari.
"Lalu..." Tidak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu. "Nah, itu dia orangnya. Sebentar, saya buka dulu."
Bu Ribka berjalan masuk menuju ruangan yang ada kursi melingkar di dalamnya bersama dengan seorang pria yang sedikit gemulai. Hal pertama yang mencui perhatian Utari adalah luka bakar di sebagian wajah dan tangan laki-laki itu. Luka di wajahnya itu bahkan sampai membuat mata sebelah kanannya menjadi seperti terpejam. Memang, kalau dilihat mata pria itu agak sipit. Lalu, Utari teringat dengan cerita adiknya tentang guru tarinya yang baru. Dari ciri-ciri fisik yang digambarkan Utami, laki-laki ini begitu mirip dengan Mas Robi.
"Utari, Bu Michelle... Kenalkan, ini teman saya, Robi." Kata Bu Ribka. Ternyata benar, dia adalah Mas Robi, guru tari Utami.
Mereka duduk dalam kursi lingkaran. Bu Ribka dan Mas Robi duduk bersebelahan. Sementara itu, Utari dan Bu Michelle duduk di hadapannya. Utari duduk di depan Mas Robi, sedangkan Michelle duduk di depan Bu Ribka.
"Jadi, dari cerita Bu Ribka, saya tahu cerita tentang kalian." Kata Mas Robi to the point. Suaranya serak-serak basah seperti mau habis. "Sebenarnya, alasan Bu Ribka menceritakan kisah kalian kepada saya bukan tanpa alasan. Saya adalah sahabat dan kerabat dekat dari orang-orang yang selama ini Anda cari."
Advertisement
Utari merinding dan tubuhnya terpaku. Ia ingin segera mendengar lanjutannya. Seperti anak kecil yang serius memperhatikan film kartun setiap minggu pagi.
"Keduanya kekasih Anda. Saya adalah salah satu sahabat dari Yudhitia." Mas Robi melihat ke arah Bu Michelle. Jantung Utari berdetak kencang.
"Saya juga adalah paman dan satu-satunya kerabat Alung atau Abimanyu yang masih hidup. Dia tinggal dengan saya setelah bapak dan ibunya meninggal dunia karena sakit." Jantung Utari semakin berdetak kencang. Entah mengapa, ia merasa semakin dekat dengan Abimanyu saat itu.
"Fakta selanjutnya, saya adalah salah satu korban dari penculikan seperti yang dialami oleh Yudithia dan Abimanyu."
"Penculikan?" Ulang Utari.
"Ya, kami semua—bertujuh—diculik secara bergantian ke suatu tempat antah berantah, di sebuah rumah yang cukup besar dan disekap disana selama berhari-hari. Abimanyu setahu saya adalah korban yang terakhir. Untungnya, saya masih bisa selamat."
"Yang laim?" Tanya Bu Michelle cemas.
"Entahlah, saya juga tidak tahu bagaimana nasib yang lainnya. Ada dua kemungkinan, mereka dibunuh atau diasingkan ke suatu pulau—seingatku namanya Cakrabyuha."
Utari dan Bu Michelle tak dapat menahan perasaan kagetnya. Mereka menutup mulut mereka masing-masing dengan tangan mereka sendiri.
Kemudian, Mas Robi menceritakan kronologi kejadian yang terjadi enam tahun yang lalu. Hal yang menimpanya dan keenam rekan lainnya di suatu malam yang hening. Ia bercerita kalau ia dan teman-temannya adalah para aktivis pergerakan anti diskriminasi etnis. Saat itu memang etnis Tionghoa sering mengalami perilaku diskriminatif. Mereka membuat tulisan-tulisan yang menyuarakan aspirasi mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan kesetaraan. Namun, ternyata usaha mereka itu dinilai sebagai suatu bentuk provokasi yang dapat memicu keonaran yang meresahkan masyarakat.
"Saya juga tidak tahu siapa dalang penculikan ini, tetapi saya yakin ini adalah ulah dari rezim yang berlaku pada saat itu. Kami dibius, lalu dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh dari Jakarta. Disana, kami disekap dan disiksa—seperti yang kamu lihat. Tidak sampai disitu, dalam penyekapan itu, mereka berencana menghilangkan ingatan kami dan membuang kami di pulau-pulau yang jauh dan tak terjangkau."
"Menghilangkan ingatan?" Utari langsung teringat kisah anak angkat Pak Jay dan ayah kandungnya. "Memang ada hal seperti itu di dunia ini?"
"Percaya, tidak percaya. Saya sendiri belum sempat masuk ke dalam alatnya—alat penghilang ingatan itu. Tetapi, para penjaga berbadan kekar itu selalu membicarakannya—seperti ibu-ibu yang sedang menggosip. Ada juga yang menakut-nakuti kami dengan bilang 'kalau ingatanmu hilang, kau akan selamat.' Dengan kata lain, hipotesis saya saat itu mengatakan, bila ingatan kami tidak benar-benar hilang atau alat itu gagal menghilangkan ingatan kami, kami akan dibunuh."
"Lalu, bagaimana Anda bisa selamat?" Tanya Utari.
"Seorang anak laki-laki seumuran Abimanyu saat itu, tiba-tiba membukakan pintu untukku dan membantuku kabur. Entah siapa dia, sepertinya anak pemilik rumah itu."
"Siapa pemilik rumah itu?"
"Seorang profesor. Entahlah, penjaga itu selalu berkata 'rumah profesor' sepanjang perjalanan ke sana. Yah, sepertinya pemerintah menyewa mafia murahan. Mereka sangat tidak profesional."
Dengan kata lain, orang itu adalah anak dari profesor itu? Jamur?
"Mengapa Anda tidak lapor polisi saat itu?" Tanya Utari tidak sabar.
"Saat saya kabur dari penyekapan itu, kondisi saya sedang parah. Saya seperti mengalami trauma fisik maupun psikologis. Maka, setelah bersusah payah kabur, saya berjuang sendiri menyembuhkan trauma dan luka-luka saya. Saya bahkan tidak bisa mengingat kejadiannya dengan jelas. Barulah, ketika bertemu dengan kerabat saya, pelaporan dilakukan. Itu setelah hampir setahun."
"Lalu?"
"Kasus kami tidak pernah ketemu ujungnya. Bahkan, saat saya memberi saksi, para polisi itu tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya ada alat yang bisa menghilangkan ingatan. Bahkan, dengan kondisi saya yang saat itu sangat parah. Anehnya lagi, ketika mereka berusaha mencari profesor yang diduga pencipta alat penghilang ingatan itu, mereka tidak dapat menemukannya. Ia menghilang seperti ditelan bumi."
Mas Robi melanjutkan, "kami sudah kelelahan menunggu kasus ini tuntas. Lalu, kami berpikir, tentu saja kasus ini sulit tuntas karena dalangnya pastilah orang yang sangat berkuasa di negeri ini."
Utari terdiam. Ia mencoba membayangkan kejadian yang barusan diceritakan oleh Mas Robi. Ia jadi semakin bertanya-tanya tentang keadaan Abimanyu. Sementara itu Bu Michelle terlihat begitu pasif, dan setengah melongok.
"Anda tidak mencari Abimanyu?"
"Tidak. Hal itu akan sia-sia saja."
"Kenapa? Anda kan pamannya!"
"Hal itu akan sia-sia saja. Pertama, dia belum tentu masih hidup sekarang. Kedua, kalau dia masih hidup, dia pasti sudah diasingkan di Cakrabyuha."
"Bagaimana kalau keadaan yang sebenarnya adalah yang kedua?" Utari terlihat tidak sabar. Dadanya naik turun. Entah mengapa, ia yakin betul kalau Abimanyu masih hidup.
"Ya, memang mungkin. Sekalipun ia masih hidup, ia belum tentu mengingatmu atau mengingat saya. Hal itu akan lebih menyakitkan, kan?"
Utari tercenung memikirkan konsekuensi itu. Tetapi, ia tidak setuju dengan pernyataan Mas Robi. Bagaimanapun, ia harus mencari tahu sendiri dan kalau apa yang dikatakan Mas Robi itu benar, ia akan membuat Abimanyu ingat lagi. Seperti Jamur, satu-satu hal yang diingatnya adalah ibunya. Masih ada kemungkinan kalau satu atau dua hal yang masih diingat Abimanyu di masa lalunya adalah Utari.
Pertemuan dengan Mas Robi, bagi Utari memberikan titik cerah. Ia terduduk di bangku sebuah kedai kopi sambil memikirkan cerita yang didengarnya hampir dua jam yang lalu di Rumah Harapan. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, bukan karena efek kopi yang sedang ia sesap, tapi karena kenyataan bahwa kemungkinan Abimanyu masih hidup dan kesempatannya untuk bertemu dengan lelaki itu masih ada. Meskipun, ia tidak tahu berapa besar kemungkinannya ia dapat menemukan pria yang telah lama menghilang itu—lebih dari enam tahun silam. Napasnya tiba-tiba agak sesak saat mengingat perkataan Mas Robi bahwa Abimanyu belum tentu dapat mengingatnya. Maka, masalahnya tidak selesai begitu saja ketika ia telah menemukan Abimanyu. Bagaimana kalau ternyata Abimanyu tidak mengingatnya? Bagaimana kalau Abimanyu, bersamaan dengan itu, juga telah melupakan perasaan yang pernah ada diantara mereka berdua? Apakah ia bisa menerimanya bila itu terjadi dan tidak akan mengubah dirinya menjadi pengais cinta Abimanyu? Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik harapannya sehingga ia hanya dapat tercenung menatap buih di dalam cangkir kopinya.
JUMAT, 2 Agustus 1991
Sebuah amplop berwarna merah muda terselip di buku sejarah yang teronggok di antara tumpukkan buku-buku lainnya di meja Utari. Saat itu, Utari baru saja masuk ke dalam kelas sambil membawa sekotak pisang goreng titipan ibunya untuk dijual ke teman-temannya di sekolah. Utari mengernyit saat melihat tumpukan buku-buku itu sudah ada di atas mejanya. Ia tidak pernah ingat kalau pernah meninggalkan buku sebanyak itu di kelas, apalagi di atas mejanya.
Amplop merah itu begitu mudah ditemukan. Ia menyembul dari sisi buku sejarah miliknya. Utari langsung menarik ujung amplop itu dan menemukan tulisan tangan seseorang yang menuliskan nama depannya tanpa basa-basi, "Untuk Utari".
Saat membuka isi amplop itu, Utari tak pernah menyangka kalau empat baris kata-kata yang tertuang di sana adalah karya seorang laki-laki yang dikaguminya. Senyum Utari merekah, jantungnya berdegup kencang. Sesaat itu juga, ia terduduk malu karena senyuman itu semakin lama semakin merekah, hingga kaki dan tangannya ikut bergerak-gerak seperti orang gemas, tak mampu ia kontrol. Pemandangan itu ditangkap oleh seorang temannya, Hendrik, yang duduk tepat di seberang kiri mejanya dengan wajah penasaran seolah-olah berkata, "Tari, apa kau baik-baik saja?"
Usai bel pulang sekolah berbunyi, Utari buru-buru merapikan buku-bukunya dan memasukkannya ke dalam tas selempang hijau yang selalu dibawanya kemana-kemana—baik ke mal, ke taman, ke warung, ke acara keluarga, pokoknya kemana pun selama tidak diprotes oleh ibu. Ia lalu berlari menuju perpustakaan. Sesampainya di depan perpustakaan, tulisan di depan pintunya terpampang "TUTUP". Bu Rida, penjaga perpustakaan, tak lama kemudian keluar dari ruangan itu sambil membawa beberapa tumpuk buku di tangannya dan tas yang tergantung di pundaknya.
"Eh, bu... perpustakaannya sudah tutup?" Tanya Utari bingung seraya melihat jam tangannya, lalu merogoh-rogoh isi tasnya, berusaha mengambil surat beramplop merah tadi. Ia ingin memastikan sesuatu.
"Iya, sudah. Ini kan sudah jam pulang sekolah."
Utari melihat isi surat itu, meyakinkan kalau laki-laki yang mengirimnya mengajak bertemu di ruang perpustakaan pulang sekolah.
"Kalau kamu mau bertemu dengan Alung, dia sudah menunggu di dalam sejak sepuluh menit yang lalu. Nanti, setelah wawancara jangan lupa dikunci ya pintunya." Bu Rida melangkah pergi menjauhi Utari yang kebingungan. Utari sekarang terpaku di depan pintu perpustakaan. Ia mengambil napas panjang—mungkin begini juga rasanya mau wawancara pekerjaan, pikir Utari setelah mendengar perkataan Bu Rida tadi.
Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbuka. Seorang laki-laki melongokkan kepalanya keluar. "Eh, ternyata kau sudah ada di sini. Mau masuk?"
Utari tergeragap, lantas mengangguk dan melangkah masuk.
Kini ia sedang bertatap muka dengan Alung yang terlihat begitu tenang, seniornya yang juga ketua osis di sekolah itu. Sementara Utari duduk tegap, tegang.
"Sebelumnya, maaf saya meminta kamu untuk datang ke sini setelah jam pulang. Bilang ya kalau risih berduaan dengan saya di dalam ruangan ini. Tapi, tenang saja saya nggak bermaksud untuk macam-macam kok." Alung memecahkan kehengingan di ruangan itu.
Utari tersenyum kaku, "Engg... Saya sama sekali tidak merasa risih kok, kak." Lalu, ia menunduk.
"Bagus kalau begitu. Saya juga sangat berterima kasih karena kamu sudah mau datang menerima undangan saya. Padahal, saya pikir kamu tidak akan datang."
"Saya yang tidak menyangka kakak mengirimkan surat itu untuk saya. Mmm... Saya, saya suka dengan kata-katanya. Tidak tahu sebelumnya kalau Kak Alung ternyata orangnya puitis." Keduanya tertawa kecil. Wajah Utari merona.
"Biasa saja, ah. Tulisan itu apa adanya saya. Duh... Saya jadi malu." Wajah Alung ikutan merona.
Advertisement
- In Serial24 Chapters

Reverie
Natalin thought that being a champion of the gods was supposed to make things easier. It turns out, life isn’t that simple. For centuries, the four gods that rule the land have each chosen a hero, a mage-warrior to act as eyes and hands in the world. Gifted with their Divine’s blessing, these Ascended and their successors have worked for centuries to ensure the land stays at peace. As the new Tideborn, the disciple of the sea god Efren, Natalin is expected to follow in their footsteps. Her counterpart Takio finds himself in the same boat, tasked with keeping his volcano goddess patron in check. The demands placed on them are immense, but together with their nations, they’ve managed to keep the peace. Until the crops and grasslands begin failing, sending Takio’s mountainous nomads careening towards war. Natalin’s shores fall under siege, destroying the seabound trade routes that keep their nations flourishing. When the very safety of the four champions is threatened by the growing chaos, Natalin and Takio realize the truth - their Divine favor won’t protect them. And there’s more at play in their ‘peaceful’ world than they’d thought. Cover art by Rin! Check out her work!
8 254 - In Serial12 Chapters

The OverGod
Warning: Tagged 18+ for sexual scenes, strong language, gore, and violenceThe Universe Particles or UPs, an unknown particle that appeared on Earth and infected all the living organisms, humans who got infected by this particle started to get sick and eventually they died. The leaders of that time employed thousands of scientists to search for the cure but to no avail. Five years later the cure still hadn’t been found but the number of deaths were increasing with each day, in these five years one billion of lives had been lost.Fearing the worst the Leaders of all countries came together and decided to build Twelve Stations underground where humans could seek shelter. Seven years later, two billions and half lives had been lost but all the stations were safely completed, but there was a problem…it couldn’t fit everyone… The leaders with this problem in hands could do nothing but choose the fittest and the best of the best in their field of work: farmers, doctors, researchers, soldiers, teachers, etc… ------------ ---------600 years later, humans are still underground…..In a white room a boy was tied on a metal chair...he never had a name, since he remembered everyone called him *Test Subject Number 7* at first he didn’t understand, but after some time he understood…He was just a Guinea Pig to these people.-----------x----------Note: English is not my native language, so bear with me please
8 54 - In Serial12 Chapters

Arpeligo
A brother and sister struggle to operate their independent interstellar transportation company within the confines of discriminatory laws and arrogant aristocratic enterprises. But fortune blows their way when they stumble upon a relatively ignorant human who also happens to be a fully authorized Citizen of the Empire, with all the legal rights and responsibilities associated with that status. Taking advantage of the situation, the sister proposes a deal to the citizen to try to secure their tiny company's future. But things are not what they seem and war between the noble families is reaching a breaking point within the sectors, causing mayhem, instability, and disastrous consequences for our interstellar crew on their trial run with the citizen. ** The setting is largely influenced by my experience in the transportation industry. I hope you enjoy it!
8 131 - In Serial7 Chapters

Steelhaven: The Rising Darkness
War rages on in the 10th millennium. Two interplanetary alliances, the Kyklos United World Alliance and the New Era Powers, are engaged in an intergalactic war that spans across the galaxy, with the latter slowly but surely achieving victory over the former. In a move of desperation, the Crown Prince of one of KUWA's allied nations, the Kingdom of Icaria, Verigan Aekarios XIII, assembles a team of specialists from across the galaxy to aid the war effort and put a stop to the NEP's progress. As our heroes begin their journey to win the Second Icarian-Orion War, they will go through many trials and tribulations. From the more obvious and direct, such as the thousands of enemy soldiers aiming for their heads, to the more inconspicuous and insidious, such as the prejudices of governors less than enthused by Verigan's course of action, as well as some... darker forces at play. Will our heroes prevail in their quest to end this war? What do these dark forces hold in store for the people of Kyklos? And is there any way to stop them? Find out in Steelhaven: The Rising Darkness! A sci-fantasy novel, collaboratively written by Denver Solace, J.P. Stefanno, Derrik S., Kezo D. Source, and a few other friends. Also available on Wattpad under the name Denver Solace.
8 199 - In Serial18 Chapters

The Rise of an Armament Emperor
A survival of a human boy who has escaped alive from a calamity and the adventure of him reaching the pinnacle!"Why? Why? WHY!?""More! More! More! I need more strength to protect everyone!""I'll never leave you behind even if my limbs been cut off!""This is all you got? Then OUT OF MY WAY! You don't even have the qualification to fight me.""Die"Hira, a boy from a small village that has been blessed with a peaceful environment and top-grade talent . But without any warning his daily life has been destroyed by the sudden attack of the demons and has been thrown into the abyss. With zero knowledge about the world, he stand up and want to find the way to survive!Schedule Release: Every week will have a guaranteed five chapter released.
8 152 - In Serial32 Chapters

The Assistant | Pietro Maximoff x Reader
Y/n L/n is just a normal girl. At least, that's what she tells the Avengers when she starts to work for Tony Stark as his assistant.Reached Number 1 in:#marvel#pietromaximoff#pietroxreader#pietromaximoffxreader#steverogers#visionReached Number 3 in:#fanfiction
8 112







 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl