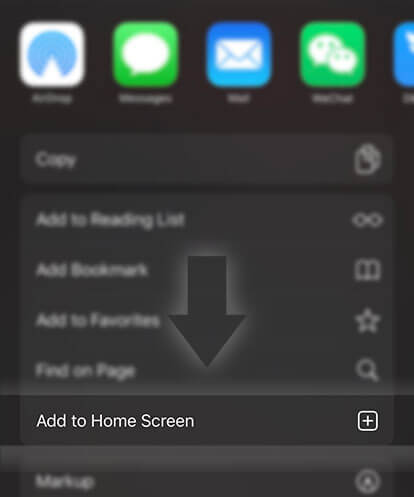《UTARI》Bab 8 - Rumah Harapan
Advertisement
UTARI sudah menunggu di Stasiun Bojong Gede saat kereta ekonomi dari Jakarta Kota yang ditumpangi Aksara sampai ke stasiun itu. Saat itu, jam tepat menunjukkan pukul 8 pagi. Utari melihat Aksara dari kejauhan. Ia turun dari gerbong tujuh—gerbong belakang—kereta itu. Ia berlari tergopoh-gopoh sambil melihat ke sekeliling. Utari berdiri dari tempat duduknya dan melambaikan tangan ke arah Aksara. Perlu beberapa lama melakukan hal itu hingga Aksara benar-benar menyadari keberadaan Utari.
"Aduh. Maaf, Utari. Kamu sudah menunggu lama, ya?" Aksara terengah-engah. Ia mengatur napasnya sambil membungkuk-bungkuk. Keringat laki-laki itu membasahi sekujur tubuh, hingga kaosnya basah. Utari mengernyit melihat pemandangan itu, namun ia hanya terdiam.
"Kenapa harus lari-lari seperti itu sih, Aksara?" Utari selalu kesulitan memenggal nama Aksara. Ia memandang iba.
"Saya takut telat. Tidak disangka, keretanya telat dari jadwal yang diberitahukan petugas stasiunnya. Jadi, estimasi saya sampai di sini setengah jam yang lalu, tidak berguna." Kata Aksara masih dalam keadaan terengah-engah.
Utari tertawa, "Makanya, saya berangkat lebih cepat. Jadwal keberangkatan kereta itu tidak bisa dipercaya. Tapi, kamu tidak terlambat kok, Aksara." Utari menunjukkan jam tangannya. "Tepat jam delapan."
Aksara mengelus dadanya. "Tapi, tetap saja saya sudah membuat kamu menunggu terlalu lama, Utari."
"Loh, janjiannya kan jam 8. Santai saja, Aksara. Nggak perlu merasa bersalah seperti itu." Kata Utari seraya tersenyum kepada Aksara. Laki-laki itu terlihat terdiam sejanak, lalu balas tersenyum.
"Terima kasih, ya." Katanya.
"Sama-sama, Aksara." Utari menepuk lengan Aksara. "Jadi, kita mau kemana sekarang?"
"Oh iya. Saya mau mengajak kamu ke suatu tempat yang ajaib—menurut saya." Mereka berjalan berdampingan keluar stasiun.
"Ajaib?" Tanya Utari keheranan. "Tempat yang kamu sebut 'Rumah Harapan' itu?" Tentu saja Utari mengerti apa yang dimaksud Aksara dengan 'ajaib' itu. Iya, hanya ingin mengetahui pendapat Aksara yang sebenarnya mengenai 'Rumah Harapan'.
"Iya. Ini bukan rumah biasa, Utari. Sudah berdiri selama kurang lebih enam tahun. Tapi, memang tidak banyak yang tahu tentang keberadaannya, sebab Rumah Harapan ini adalah komunitas rahasia."
"Komunitas rahasia?" Utari bertanya lagi.
"Sebenarnya tidak bisa dibilang rahasia juga, tapi di dalam komunitas itu, setiap orang bersepakat untuk menjaga rahasia masing-masing. Mereka mungkin lebih cocok disebut dengan social support group. Anggota mereka juga tidak bertambah sejak pertama kali didirikan, sebab mereka tidak membuka rekrutmen terbuka karena dikhawatirkan akan mengacaukan kegiatan dalam komunitas itu sendiri. Kalaupun ada anggota baru, bertambahnya tidak banyak bisa dihitung dengan jari dalam selang waktu sempat sama lima tahun."
Aksara menyetop sebuah angkot berwarna merah yang hendak melintas di jalan dekat Stasiun Bojong Gede, lalu mempersilakan Utari masuk ke dalam angkot itu duluan. Mereka duduk berhadapan. Angkot tidak terlalu penuh saat itu. Hanya ada dirinya, Aksara dan seorang ibu dengan bayi yang sedang tidur di pangkuannya. Sopir angkot yang kelihatan masih bocah itu menyetel musik dangdut agak lirih.
Utari menunggu Aksara bercerita lagi soal 'Rumah Harapan,' namun lelaki yang duduk di depannya itu memberika tanda pada Utari. Ia menempelkan jari telunjuk kanannnya di bibirnya. "Tidak bisa cerita disini," kata Aksara lirih.
Utari hanya mengangguk.
"Omong-omong, kamu benar-benar tidak jadi bertemu temanmu? Padahal, tujuan kita kan sama. Kalian janjian di Bojong Gede juga, kan?"
"Tidak jadi. Lagipula, nanti juga ketemu."
"Maksudnya?"
"Iya, nanti juga ketemu di lain kesempatan, maksud saya." Utari tersenyum. Lelaki di depannya memasang muka habis dikerjai.
"Berapa lama kita akan sampai disana?"
"Tidak lama. Hanya sekitar 30 menit naik angkot. Lalu, nanti kita jalan kaki atau naik ojek."
"Ojek?" Utari refleks bertanya kepada Aksara karena setahunya tidak ada tukang ojek di dekat Rumah Harapan. Tapi, sesaat kemudian ia menyesal menanyakan hal itu.
"Iya, ojek. Kenapa?"
"Tidak apa. Bertanya saja karena kalau begitu, berarti harus sewa dua ojek untuk sampai ke sana, dong." Utari tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi, ia rasa apa yang diungkapkannya barusan sukses membuatnya terlihat bodoh di depan Aksara.
Advertisement
"Iya. Kenapa? Kamu mau sewa satu ojek saja, lalu kita naik motor bertiga?" Aksara tertawa meledek Utari. Perempuan itu tertunduk tersipu malu. Ibu yang sedang duduk di samping Utari, menegokkan kepalanya karena merasa terusik dengan suara tawa Aksara, mungkin.
Sebenarnya, ada yang sangat ingin Utari tanyakan kepada Aksara sejak pertama kali laki-laki itu mengajaknya ke Rumah Harapan: apa maksud Aksara mengajaknya kesana—terlepas dari kenyataan bahwa dirinya adalah anggota dari komunitas itu. Tapi, ia merasa ragu, entah kenapa. Lagipula, situasinya saat ini tidak memungkinkannya untuk bertanya lagi tentang Rumah Harapan kepada lelaki itu.. Aksara tidak ingin pembicaraan mereka didengar orang karena yang sedang mereka bicarakan adalah sebuah komunitas rahasia. Namun, sekarang Utari jadi penasaran, darimana Aksara mengetahui keberadaan dan informasi mengenai komunitas itu.
Di tengah perjalanan menuju Rumah Harapan, tidak banyak hal yang mereka bicarakan. Baik Utari maupun Aksara lebih banyak diam. Dari sudut matanya yang sedang melihat ke kaca mobil bagian depan, yang terhalang oleh kepala supir angkot itu, ia melihat wajah serius Aksara. Lelaki itu seperti sedang memikirkan sesuatu di dalam diamnya, entah benar atau tidak terkaan Utari itu.
Aneh, kata Utari dalam hati, menyadari sesuatu. Ia melihat telapak tangannya yang kering. Ia sama sekali tidak merasakan apapun. Tidak seperti saat ia bertemu dengan Pak Jay beberapa hari yang lalu. Kondisi yang menyebalkan itu memang hanya muncul ketika ia berhadapan dengan orang-orang tertentu saja, seperti kesembilan belas orang yang tertulis di buku catatan merah marunnya. Ketulusan seseorang dan ketidaktahuan Utari akan perasaan orang lain membuatnya merasa nyaman berada di dekat orang itu. Sudah lama ia tidak bercakap dan pergi berdua dengan seorang laki-laki. Yang jelas, bersama Aksara, ia tidak merasa takut dan cemas.
PIKIRAN Utari melayang ke kejadian hampir lima tahun yang lalu. Tentang jalan yang mengantarnya ke pintu Rumah Harapan. Saat itu, Utari duduk di suatu bar & coffee shop bernuansa kayu yang tidak terlalu ramai, bahkan bisa dikatakan sepi. Utari duduk di salah satu meja. Seorang waiter berpakaian serba hitam yang kepalanya ditutupi oleh syal berwarna biru menghadap ke Utari. Perempuan itu duduk dengan punggung yang tegak. Mata Utari membesar, menunggu pertanyaan dari sang waiter yang ia yakin tidak dapat dijawabnya dengan baik itu.
Utari mengambil sebungkus rokok dari tasnya lalu menyalakannya.
"Ada yang bisa dibantu?"
"Mmm..." Utari terlihat ragu. Ia baru pertama kali berniat memesan minuman keras. Utari sudah beberapa kali merokok diam-diam. Tapi, sekalipun perempuan itu tidak pernah menyentuh minuman keras. Perasaan takut menghalanginya, takut dosa. Namun, perasaan kehilangan dan tuntutan orang-orang di sekitarnya yang dirasakannya saat itu membuatnya ingin mencoba "minum".
"Saya baru pertama kali minum. Kalau Anda berkenan, beri saya minuman yang paling baik untuk pemula seperti saya." Kata Utari setelah menghisap rokoknya.
Waiter itu tertawa, lalu menyebutkan sebuah merek beer yang terlupakan begitu saja.
"Ya, apa saja. Saya ingin mabuk."
Waiter itu tersenyum, mencatat pesanan Utari dan pergi menuju meja bar.
Seorang perempuan yang sedari tadi duduk di pojok ruangan sambil membaca koran, tiba-tiba sudah berada di sampingnya. "Sendirian? Boleh saya duduk di sini?"
Utari melihat perempuan itu dengan tatapan heran. Sungguh aneh meminta kursi di private table suatu kedai kopi kepada seseorang padahal masih ada banyak meja kosong di sana. Namun, tak sepatah katapun keluar dari mulut Utari saat itu. Ia hanya terpana melihat perempuan itu bergerak menarik kursi dan menjatuhkan bokonnya di atas kursi itu. Sekarang mereka berhadapan dan Utari merasa sedikit canggung sepeti baru tersadar dari lamunannya.
"Maaf, ada keperluan apa? Masih banyak meja yang kosong di sini." Kata Utari sambil mematikan rokoknya di asbak.
"Faktanya, hanya kita berdua yang berada di kafe ini. Saya sebenarnya sedang menunggu seorang teman, namun tiba-tiba ia membatalkan janjinya. Saya bukan tipe orang yang terlalu senang menikmati makan atau minum seorang diri. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin duduk di sini sambil mengobrol-ngobrol."
Advertisement
Hal itu terdengar seperti minta izin. Tetapi, kenyataannya perempuan itu sudah duduk di salah satu kursi di mejanya. Utari mengernyitkan dahi. Lagi-lagi ia terpaku dan tidak bisa mengusir perempuan itu. Padahal, alasan ia pergi ke kedai kopi ini siang itu karena ingin menyendiri.
"Baru pertama kali minum, ya?" Tanya perempuan itu. Tak lama kemudian, seorang waiter datang sambil membawa nampan yang berisikan gelas dan sebotol beer, dan semangkuk es batu dan penjapitnya.
"Iya. Memang kenapa?"
Perempuan itu lalu bercerita tentang ayahnya yang menjadi seorang pemabuk setelah ditinggal pergi oleh ibunya bertahun-tahun silam. Lalu, ia juga dulu pernah menjadi seorang pemabuk, semenjak laki-laki yang amat dicintainya pergi meninggalkannya, tanpa pamitan, tanpa meninggalkan jejak apapun, sehingga ia tidak dapat mengikutinya.
Utari mendengarkan cerita perempuan itu dengan seksama dan menghirup aroma sendu yang keluar dari nada bicara perempuan itu. Bibir perempuan itu tersenyum mengenang sesuatu, namun matanya layu. Utari berkata dalam hati, perempuan itu punya sakit yang sama dengan yang dirasakannya saat itu. Mungkin bila perempuan itu tidak menceritakan hal semacam ini, Utari lama-lama tidak akan segan mengusirnya. Ternyata ada orang yang merasakan musibah yang sama seperti yang ia rasakan. Ia tidak sendirian.
"Tapi, saya sadar. Semua itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Alih-alih lupa, saya justru sering dihantui dengan bayangan laki-laki itu. Yang lebih buruk lagi, saya membiarkan diri saya hancur." Perempuan itu berhenti berbicara, lalu menelan ludahnya. "Bukankah ini sangat ironis, mengorbankan diri dan tubuh sendiri karena orang yang bahkan tidak memikirkanmu, meninggalkanmu. Sayangnya, teori seperti itu tidak terlalu mempan untuk sebagian orang—yang sudah jatuh terlalu dalam ke lubang masa lalu. Mereka bahkan menolak melupakan masa lalu dan melihat kedepan dan tak ingin melepaskan hal itu."
Menolak melupakan masa lalu. Kata-kata itu mengiang di kepala Utari. Perasaan tidak tenang muncul di dalam dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kalimat itu bila ia memasukkan konteks dirinya di dalam kalimat itu, seperti ada yang berlawanan dan saling berbenturan. Masa lalu yang ada di kepalanya juga berarti masa depan baginya, sehingga bila ia melepaska masa lalu itu sama saja ia melepas masa depannya.
Lalu, perempuan itu memberikan kartu namanya. Tertulis di atas kartu nama itu "Rumah Harapan" dan nama perempuan itu adalah Ribka Suroto. Di bawah kartu nama itu tertulis sebuah kalimat, "Tak ada hal yang menetap di dunia ini." Sebelum perempuan itu pergi meninggalkannya, ia mengatakan kepada Utari, "kalau kamu mendengar suara-suara aneh, jangan ragu-ragu untuk datang." Apalagi setelah Utari secara sadar menceritakan sendiri hal yang membuatnya hatinya gundah. Dunia ini rasanya berhenti ketika ia tahu Abimanyu telah pergi dan entah kapan akan kembali. Meski begitu, ia yakin Abimanyu akan kembali.
Setelah turun dari angkot, Aksara mencari ojek di sekitar jalan yang menuju Rumah Harapan. Namun, mereka tidak menemui satupun tukang ojek yang ada di pangkalan. Utari bertanya-tanya, sejak kapan ada tukang ojek di sini, sambil melihat papan bertuliskan "OJEK" yang terpaku di salah satu pohon yang di depanya terdapat bangku dipan.
"Kenapa tidak jalan saja?" Tanya Utari.
Aksara terdia sebentar, seperti sedang berpikir. Memang jarak dari ujung jalan yang tidak diaspal itu dan Rumah Harapan cukup jauh. Sekitar 30 menit berjalan kaki. Sementara itu, hanya ada satu dua rumah dan pepohonan yang akan mereka temui selama perjalanan itu. Biasanya, setiap hari minggu para anggota Komunitas Rumah Harapan itu akan menelusuri jalan ini dengan menenteng buku catatan kecil berwarna merah marunnya. Seperti jemaat gereja yang menenteng Injil-Injil mereka dengan pakaian rapi setiap minggu pagi. Namun, kali itu jalanan sepi, seolah mempersilakan Utari mendengarkan cerita Aksara mengenai Rumah Harapan tanpa bias yang muncul karena pengetahuan bahwa dirinya adalah anggota dari komunitas itu.
"Kalau ini komunitas rahasia, lantas kamu tahu darimana informasi mengenai komunitas ini?"
"Salah seorang temanku di Jerman pernah meneliti tentang komunitas ini. Aku tertarik unruk melihatnya langsung."
"Lantas, kenapa begitu ingin mengajakku ke sana?" Tanya Utari langsung agak melebih-lebihkan. "Maksudku, kamu bilang di SMS, aku harus tahu mengenai komunitas ini."
"Jawabannya tidak sederhana, Utari. Tapi, kalau kau ingin tahu pendeknya, aku tahu apa yang kau rasakan selama kurang lebih enam tahun belakangan ini."
"Tahu? Apa yang aku rasakan?" Ulang Utari.
"Bagaimana bisa? Sementara kita, setelah empat tahun berselang, baru bertemu sekali saat pernikahan Mas Seno. Kita bahkan tidak pernah mengobrol." Utari tertawa, atau lebih tepatnya menertawai Aksara. "Sok tahu kamu."
"Ya, makanya aku bilang ceritanya tidak sesederhana itu. Kamu pasti bertanya-tanya tentang bagaimana aku bisa menerka hal semacam itu. Padahal apa yang aku terka adalah soal hati. Bukankah tak ada yang mengerti tentang hati seseorang kecuali dirinya sendiri. Hmm... Oh tidak, maksudku kecuali Tuhan."
"Lalu?"
"Nanti saja aku ceritakan. Tenang, aku janji akan menceritakannya. Tapi, tidak sekarang." Aksara menengokkan kepalanya ke arah Utari, dan tersenyum. Sementara itu, kaki mereka terus melangkah menyusuri jalan berbatu yang agak menurun itu.
"Baiklah. Aku akan menunggu saat itu." Kata Utari tanpa melihat Aksara. Ia berusaha untuk tetap terlihat tenang, meskipun dirinya sangat ingin tahu bagaimana Aksara dapat menerka hal semacam itu. Terlalu acak.
Seorang perempuan paruh baya menyambut Aksara dan Utari. Dia adalah Bu Ribka, orang yang memberikan kartu namanya pada Utari dan mempersilakannya untuk bergabung dengan komunitas itu.
"Selamat datang, Aksara dan Utari." Kata Bu Ribka sambil merentangkan kedua tangannya. Utari menyambutnya dengan pelukan. "Sudah lama ya, Bu."
"Eh?" Aksara terlihat kebingungan melihat pemandangan yang ada di depannya. "Utari kenal dengan Bu Ribka?" Tanyanya terbata-bata.
Utari dan Bu Ribka hanya tersenyum.
"Bagaimana, Utari? Sudah ada kemajuan belum?" Tanya Bu Ribka sembari merangkul Utari dan berjalan ke dalam ruangan. "Sudah orang kesembilan belas, bu."
Ruangan itu berisi bangku-bangku yang membentuk melingkar. Hanya ada sekitar 10 bangku dan sudah enam bangku yang terisi. Semuanya sedang sibuk melihat-lihat isi buku catatan kecil mereka dengan serius.
"Ibu-ibu, perhatian! Kita kedatangan anggota baru. Namanya Aksara." Kata Bu Ribka kepada orang-orang yang ada di ruangan itu. Tidak ada yang bersuara, namun mereka terlihat heran saat melihat Aksara. Mungkin, baru kali itu mereka melihat anggota Rumah Harapan yang berjenis kelamin laki-laki.
Aksara tersenyum dan melambaikan tangannya. "Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aksara." Kata Aksara dengan ceria. Ibu-ibu itu mengernyitkan dahinya melihat sikap Aksara, begitu juga dengan Utari.
"Baiklah, Aksara dan Utari silakan duduk di dalam lingkaran." Kata Bu Ribka.
"Maksud kamu apa sih, Aksara?" Bisik Utari.
Aksara menggeleng cepat. "Aku kesini maksudnya ingin bermain saja. Bukan ingin jadi anggota." Balas Aksara.
AKSARA bergabung ke dalam lingkaran itu. Selama beberapa lama, mereka hanya duduk sambil memperhatikan tulisan yang ada di dalam buku catatan kecil mereka masing-masing. Utari duduk tepat di sebelah Aksara, dan ia tidak terlihat melakukan hal serupa seperti ibu-ibu yang ada di situ. Aksara memalingkan wajahnya ke arah Utari, lalu mendekatkan kepalanya ke telinga Utari.
"Kamu, kenapa tidak mengeluarkan buku merah itu? Kamu punya, kan?"
Utari melihat kearah Aksara dengan pandangan heran. "Aku masih bingung dengan maksud kamu, Aksara."
"Jadi, karena ada saya di sini kamu tidak mau mengeluarkan buku itu? Baiklah, saya pergi saja dari sini. Jadi tidak enak saya."
Aksara beranjak dari tempat duduknya. Utari tidak berusaha mencegahnya. Lelaki itu berulang kali menengok ke arah Utari yang seperti terpaku di tempat duduknya. Ia lalu pergi ke ruangan di sebelah ruang yang berisikan bangku yang melingkar itu dan duduk di sana. Dari tempatnya, samar-samar ia dapat mendengar pembicaraan mereka. Beberapa orang memasuki rumah itu dengan membawa buku catatan kecil merah marun mereka dan menatap heran ke arah Aksara.
"Heh, Aksara. Kamu tidak mau ikut duduk?" Tanya Bu Ribka.
"Tidak, bu. Saya di sini saja. Utari tidak konsentrasi mengikuti diskusinya kalau ada saya di sana. Mungkin karena ia mengenal saya."
"Baiklah kalau begitu, ibu biarkan pintunya terbuka, ya. Jadi, kamu bisa tetap mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Jangan kaget kalau ada yang tiba-tiba menangis atau berteriak-teriak, ya." Kata Bu Ribka.
Aksara hanya mengangguk.
Dari ruangan itu, Aksara dapat mendengar apa yang didiskusikan para perempuan itu. Setiap hal yang didengarnya membuatnya mengernyit. Hal-hal yang disebut di dalam kelompok diskusi itu sangat asing kalau tidak mau dibilang aneh oleh Akasara. Hampir semua dari mereka mengaku mendengar suara-suara yang membisiki mereka. Sebagian ada yang muncul begitu saja, sebagian lagi ada yang harus dipanggil dulu. Suara-suara itu memberitahu keadaan orang-orang di kehidupan mereka yang hilang atau berusaha untuk membuat harapan akan kembalinya orang-orang itu di kehidupan mereka. Hal itu lah yang membuat mereka tidak dapat juga beranjak dari masa lalunya.
Seorang perempuan tiba-tiba menangis ketika ia mendapat telepon dari polisi bahwa mayat anaknya telah ditemukan mengapung di suatu sungai yang jorok di Jakarta. Tubuhnya telah kaku dan banyak sampah yang menyangkut di sana. Lalu, suara-suara itu memberitahunya kalau anaknya masih hidup, tapi keadaannya tidak terlalu baik. Perempuan itu kebingungan, lantas berteriak-teriak sambil menangis. Ia tidak ingin percaya dengan kabar yang diberikan polisi karena suara-suara itu mengatakan hal yang bertolak belakang.
Advertisement
- In Serial979 Chapters

Yama Rising
The youthful Qin Ye was born almost a century ago, but thanks to immortality granted to him by the 'fungus of aeons' he can pass for a high schooler. He planned to live an eternal, reclusive life as a happy otaku, enjoying World of Warcraft and his favorite MOBA games, but Fate had other plans in store. Hell has broken down, and vengeful revenants stalk the mortal realms. With ghosts running amok throughout all of Cathay, Qin Ye must reluctantly adopt the mantle of 'hero' and bring peace to both the living and the dead, while rebuilding Hell. But this, of course, isn't something a mere Netherworld Operative can do. For that, he'll need to become more.King Yama is dead. Long live King Yama!
8 741 - In Serial23 Chapters

Path of Jade
The Emperor has been murdered, leaving the Qeitan Dynasty in chaos. Liao is a privileged prince and Seer, possessing the power to see the past, present, or future. Witnessing a vision of the future foretelling his fate: his kingdom razed, ascending the throne and leading to his death, he must unravel the threads of his prophecy before it is completed. As Liao discovers more of the truth, kingdoms burn – and empires make their move. Yvir is a lowly tavern brawler, fighting only to pay off her debt and her mother’s. Taking a job to clear what they owe, Yvir finds herself caught in a conspiracy spanning continents. Jhong is Headsman of the most powerful syndicate in Qeita. Despite his influence, he still lurks in the shadows, away from the bright eyes of the immortals. Where one would find themselves overlooked, Jhong sees opportunity, and he'll seize his prize: all of Qeita, even if it means killing people who consider themselves unkillable. The fate of an empire hangs in the balance, and blood is spilled in the scale of rivers. There is only one path seen – set with secrets, brutal truths, and the eternal conquest for immortality: a path of Jade. A Grimdark Fantasy saga inspired by the ancient Chinese epic Romance of the Three Kingdoms, R.F. Kuang's The Poppy War, George R.R. Martin's A Game of Thrones, Mark Lawrence's hauntingly dark tone, and the prophetization of Frank Herbert's Dune.
8 245 - In Serial6 Chapters

Dark Crow Rising
Beyond the Anvil-Peak Mountain surrounded by a sea of molten gold. There lies a city that spans two continents, its origins going back to the time of gods. Where Thunder struck thrice to defend the world. Further beyond, the tallest mountain in the world from which all wind is born. It is a land of much stone beauty and arcane horror, and one man from a land of no magic... Finds himself stuck there and exposed to its worse first.
8.18 88 - In Serial29 Chapters

What to do? High school! #Thewattys2018
Date: 10/6/17High school. Think about it. How was your high school experience? Good, bad, in the middle? Well, this is the story of one group of friends, with 8 teenagers in it. Drama, love, hate, and most of all, the story of how a true friendship can get through anything.
8 125 - In Serial8 Chapters

Electric (Phillip Carlyle x OC) ~DISCONTINUED~
Just a little fanfic I made up with the help of wildmustang4002 who inspired me to write this story!
8 73 - In Serial8 Chapters

Breathe me || Jeongyeon x MoMo
-A beautiful smile doesn't mean a beautiful life.
8 139







 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl