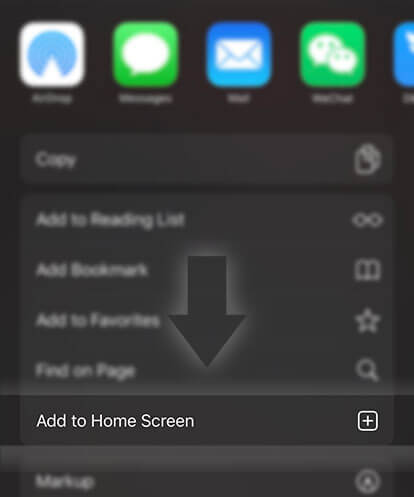《UTARI》Bab 7 - Seorang Anak yang Berwajah Ceria
Advertisement
Utari dan Laras sampai rumah pukul 8 malam karena terjebak macet di jalan. Ibu bertanya apa yang mereka lakukan di luar dan apa yang mereka bicarakan. Laras mengatakan kalau mereka membicarakan rencana pernikahnnya dengan Ridwan, tanpa tendeng aling-aling. Ibu mengerutkan dahi, lalu melirik Utari yang sedang pura-pura mengalihkan perhatian sambil membuka tudung saji di meja makan. Sementara itu, Laras pergi ke kamarnya di lantai dua.
"Itu apa?" Ibu menanyakan bingkisan besar yang Utari letakkan di pojok ruangan.
"Nggak tahu, belum Utari buka. Kado dari teman Tari."
"Ulang tahun kamu kan masih lama."
Utari tidak menjawab. Ia sibuk mengunyah tahu goreng yang diambilnya di meja makan. Meski sebenarnya pikirannya sedang tidak berada pada tahu goreng yang sekarang ada di tangan dan di dalam mulutnya.
"Eh, Utari. Tadi adik kamu bilang apa?" Tanya ibu setengah berbisik pada Utari.
"Ya, intinya dia keukeuh mau menikah dengan Ridwan." Utari melahap tahu gorengnya lagi.
"Nduk, coba kamu ambil positifnya dari keinginan adikmu itu. Jangan dimasukkan ke hati." Kata ibu. Utari menerka ibunya menyangka ia tersinggung. Mungkin karena Utari bicara tanpa melihat matanya
"Mbak Utari setuju kok, bu. Sebentar lagi juga akan bawa calon suami ke rumah." Laras tiba-tiba muncul dengan wangi sabun yang menusuk dan rambut yang basah. "Iya kan, mbak?" Katanya sambil tersenyum.
Utari menatap adiknya tidak mengerti.
"Oh, jadi kamu sudah punya calon toh, Tari? Coba dikenalkan sama ibu. Eh, iya... orang mana?"
"Opo toh, bu... Ngarang itu Laras."
"Masa? Terus yang ngasih lukisan gambar mbak sebagus itu siapa?"
Utari langsung beranjak menuju ruang makan, tempat ia meletakkan bingkisan dari Pak Jay. Ibu dan Laras mengikuti dari belakang. Laras meletakkan lukisan itu di atas bangku sehingga siapapun yang masuk ke dalam ruangan itu dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat foto dirinya di sana, begitu nyata seperti gambar yang diambil dengan kamera profesional. Utari tidak pernah tahu kalau Pak Jay pandai melukis, sampai ia melihat inisial nama di pojok lukisan itu. J.M (Jayadi Murat).
"Wah, bagus sekali lukisannya, nduk. Kamu kelihatan cantik di sini." Ibu sumringah.
"Ada suratnya tuh, mbak. Tenang... belum aku buka kok." Kata Laras sambil menunjuk sebuah amplop yang ada di dalam tas bingkisan itu. Tetap saja ia lancang membuka bingkisan orang tanpa izin dulu, pikir Utari.
Ibu mendekatinya yang sedang membuka surat, ingin tahu. Tapi, Utari menghindarinya dan membaca surat itu di ruang tamu. Dari sana ia tahu kalau yang membuat lukisan itu bukan Pak Jay, tetapi anaknya yang berusia 12 tahun. Pak Jay menuliskan kalau anaknya pernah melihat dirinya di kantor. Semenjak saat itu, anaknya tidak bisa melupakan wajah Utari karena katanya wajahnya mirip dengan almarhumah ibunya. Semenjak saat itu pula ia mulai memperhatikan Utari dan baru menyadari apa yang dilihat oleh anaknya. Titik.
"Apa isi suratnya, Utari? Ini dari siapa toh?"
"Dari teman kantor aku, bu."
"Lukisannya bagus. Dia seniman?"
"Bukan. Itu bukan lukisannya. Itu lukisan anaknya."
"Orang yang suka sama mbak sudah beristri?!" Pekik Laras. Entah bagaimana Laras bisa langsung menyimpulkan bila seseorang sudah memiliki anak, dia pasti sudah punya istri.
Utari mengangguk. "Tapi sudah meninggal—mbak juga baru tahu."
"Bagaimana? Ibu mau anaknya menikah dengan duda usia 45 tahun dan beranak sekian—aku tidak tahu anaknya berapa." Tantang Utari.
"Kenapa nggak?" Jawab ibu tanpa pikir panjang. Utari mendengus.
"Sudah, ah. Aku mau mandi dulu." Utari meninggalkan ruang tamu, mengambil lukisan pemberian Pak Jay berikut suratnya dan membawanya ke kamar.
"Bu, Utami belum pulang. Dia kemana ya?" Tanya Utari sebelum masuk kamar, mengingatkan ibu agar menghubungi adik bungsunya itu. Ibu bilang mulai hari ini, setiap sore, Utami harus pergi ke sanggar untuk latihan tari yang akan ditunjukkannya di Festival Tari.
Advertisement
UTAMI baru sampai rumah pukul setengah dua belas malam. Saat itu, Utari sedang menonton TV di ruang tamu. Ia pulang ke rumah dengan wajah kelelahan, namun tidak terlihat kesal. Ya, semenjak Utami bilang ada guru tari baru yang bernama Mas Robi di sanggarnya, ia selalu pulang dengan mulut manyun dan wajah lecek. Tapi, kali itu tidak. Utari seperti melihat diri Utami yang dulu, yang selalu semangat belajar menari dan bercita-cita menjadi penari profesional.
"Eh, Mbak Tari belum tidur? Ibu mana?" Kata Utami seraya mencium tangan kakaknya. Lalu, ia duduk di samping Utari dan menyandarkan punggungnya ke sofa.
"Ketiduran sepertinya. Kamu kenapa malam-malam betul sih pulangnya, Tam? Biasanya nggak semalam ini."
"Aku terpilih jadi wakil kota untuk Festival Tari Nusantara, mbak. Jadi, mulai hari ini, selepas sekolah aku harus latihan keras. Kadang bisa sampai jam segini karena banyak tarian yang harus aku pelajari."
"Wah, repot juga kamu. Sekolahmu nggak bermasalah?"
"Aku sudah izin dengan pihak sekolah. Katanya pak kepala sekolah mendukung. Tapi, aku juga tidak mengerti bentuk dukungannya seperti apa. Mudah-mudahan saja diberikan jatah untuk tidak masuk sekolah atau diberi keringanan untuk masuk sekolah lebih siang. Sulit juga rasanya kalau harus latihan sampai semalam ini, besoknya masuk sekolah jam 7 pagi."
"Mana bisa begitu. Itu sih harapan kamu saja, Tam. Yang penting jangan sampai mengganggu sekolah. Bilang sampai Mas Robi kalau kamu masuk jam 7 setiap hari. Kalau tidak keburu, lebih baik setiap weekend dimaksimalkan latihannya." Kata Utari sambil menatap adiknya yang matanya sudah terlihat sangat kelelahan itu.
Adiknya malah tertawa. Mungkin menyadari kalau yang barusan dikatakannya hanyalah harapannya semata. "Oh iya, mbak. Omong-omong tadi Mas Robi tidak datang mengajar. Sebagai gantinya, ada guru tari baru yang jauh lebih manusiawi mengajarnya. Ganteng lagi. Makanya, hari ini aku latihannya semangat." Tambah Utari sambil cekikikan.
"Dasar kamu. Memangnya kemana Mas Robi-mu itu? Masa baru mengajar di sana sebentar sudah digantikan lagi."
"Aku juga nggak tahu Mas Robi itu tidak masuknya sementara atau selama-lamanya. Yah, mudah-mudahan saja selama-lamanya."
"Kayaknya benci banget ya kamu sama Mas Robi itu. Ckck." Utari berdecak. Dari luar terdengar gemuruh. Sepertinya malam itu akan hujan lagi.
Utami sudah pergi untuk mandi dan tidur. Sementara itu, Utari masih sibuk memindah-mindahkan saluran televisi—mencari-cari program tengah malam yang menarik untuk ditonton. Suatu program acara berita sedang menayangkan liputan perayaan Imlek hari itu. Utari memperhatikan tayangan yang menunjukkan orang-orang yang sedang berdoa di wihara dengan menggunakan dupa berwarna merah dan pertunjukan barongsai yang sangat meriah dan bisa dinikmati baik oleh masyarakat keturunan Tionghoa sendiri atau bukan. Reporter acara berita itu membacakan narasi selama tayangan itu berlangsung:
"Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia diperbolehkan untuk merayakan Imlek secara terbuka di tahun 2000, setelah rezim pemerintahan Soeharto berakhir. Rezim yang sudah berlangsung selama 32 tahun ini runtuh dalam sebuah kekerasan massal, dimana etnis Tionghoa dijadikan sebagai sasaran utama dalam kerusuhan. Tahun ini pun, diharapkan akan membawa kedamaian yang lebih langgeng."
Suatu waktu Abimanyu pernah berkata pada Utari, "zaman ini, tidak mungkin ya pergi beribadah tanpa melihat adanya petugas keamanan atau polisi berjaga yang jumlahnya menyaingi jumlah jemaat. Walaupun aku tidak ikut merayakan di wihara atau klenteng, aku sering memperhatikan hal-hal seperti itu. Aku bingung."
"Bingung kenapa?"
"Manusia itu sepertinya lebih takut bom dibandingkan Tuhan. Padahal, kalau mereka mati saat beribadah kan mereka bisa langsung bertemu Tuhan mereka. Siapa tahu juga bisa langsung masuk surga, istilahnya mungkin bisa disamakan dengan mati syahid. Jadi, tidak perlu ada petugas keamanan berjaga di tempat-tempat ibadah."
Utari tertawa, "Ngaco kamu. Biar bagaimanapun, yang salah itu para terorisnya. Mereka pikir mereka akan masuk surga dengan mempercepat jalan orang-orang yang sedang beribadah untuk menemui Tuhannya."
Advertisement
Abimanyu tersenyum kecil sambil menatap Utari lekat dengan matanya yang kecil dan berwarna cokelat. Senyuman itu, salah satu hal yang paling disukai Utari di dunia ini. "Perkataanku memang kacau. Pasti karena dunia ini juga semakin kacau, Utari. Tapi, tak apa selama ada kamu di sampingku, aku tidak pernah mengambil pusing atas kekacauan itu." Mereka lalu berjalan berdampingan. Utari dapat melihat punggung mereka berdua menjauhinya menuju tempat penuh cahaya.
Sampai pagi datang, Utari terlelap di atas sofa ruang tamunya. Ia bermimpi bertemu dengan Abimanyu. Ia berkata pada lelaki itu dengan terbata-bata, "sudah...delapan...belas."
SEIKAT bunga mawar merah segar dan kantong berisi kue keranjang dari Azalea tergeletak dengan manis di atas meja kerja Utari saat ia baru sampai di kantor. Tangkai bunga-bunga itu dipotong pendek dan ia diletakkan di dalam vas bunga bening yang didalamnya dituang air. Sebuah post-it tertempel di sisi vas bunganya.
"Bunga cantik untuk mahluk cantik seperti kamu –Jay." Kali ini kalimat cheesy itu dikarang sendiri oleh Pak Jay. Utari memiringkan bibirnya.
Seperti biasa, Sirene muncul tiba-tiba di depan kubikalnya dengan tatapan menggoda. Lalu, ia bertanya apakah ia suka dengan hadiah yang diberikan oleh Pak Jay. Utari tidak mengacuhkan pertanyaan Sirene dan menyalakan desktop-nya.
"Utari, kamu bisa merasakan kan kalau anak Pak Jay itu suka sekali dengan kamu. Bahkan katanya ia ingin bertemu kamu... ups." Sirene menutup mulutnya dengan jari-jari yang kukunya berwarna pink neon. Utari tidak menanggapi, tapi dadanya tersentak.
"Usianya baru delapan tahun dan dia pernah dibawa ke psikolog karena depresi dan kerap kali mengamuk karena ditinggal mati oleh ibunya. Pak Jay bilang, setelah melihat kamu anaknya kembali punya semangat hidup. Yang kamu terima itu bahkan hanya satu dari sekian banyak lukisan diri kamu yang dibuat oleh anak Pak Jay."
Tubuh Utari bergidik. Apa lagi sih ini? Ia tidak tahu apakah perkataan Sirene itu benar atau hanya karangannya saja agar ia bersimpati kepada Pak Jay. Lagipula, bagaimana bisa ia berbuat sebanyak—sesignifikan—itu untuk seseorang yang bahkan belum pernah dikenalnya sebelumnya. Padahal, ia tidak melakukan apapun.
Kali ini Utari tertarik untuk bertanya pada Sirene. Ia memutar kursinya, "Sirene, kali ini aku bertanya serius. Apa yang kamu katakan tadi itu benar? Karena kalau ternyata cerita itu hanya karangan, apa yang kamu lakukan sia-sia saja."
"Menurutmu, untuk apa aku mengarang-ngarangnya?"
"Untuk mendapatkan simpatiku... mungkin. Sebab kejadian seperti ini terlalu sulit untuk dipercaya. Seorang bapak yang mendekati seorang perempuan hanya karena anaknya menyukai perempuan itu saat melihatnya. Oh, dramatis sekali!"
"Yah, aku tahu ini terlalu aneh. Sekali waktu Pak Jay pernah menunjukkan foto mendiang istrinya kepadaku dan... Ya Tuhan, Utari... kamu pasti tidak pernah tahu kalau kamu sebenarnya punya kakak kembar." Kata Sirene, cara bicaranya dibuat-buat sok centil. Ia menempelkan kedua telapak tangannya di pipinya.
Utari mendengus. Pembicaraan Sirene semakin kacau, sebab ia adalah anak sulung di keluarganya. Kakak Utari telah meninggal di dalam kandungan beberapa hari sebelum bayi itu siap lahir. Tapi, ia mengerti Sirene berkata seperti itu hanya untuk menunjukkan kalau wajah mendiang istri Pak Jay begitu mirip dengannya. Tetap saja ini konyol dan tidak mudah diterima begitu saja dengan akal sehat Utari dan siapapun yang mendengarnya.
"Shiren... Boleh aku menitip pesan untuk Pak Jay melalui kamu?"
"Tentu saja. Aku kan di sini ada untuk membantu kalian." Katanya tersenyum genit.
Utari semakin penasaran mengapa Sirene sebegitu gencarnya mempersatukan dirinya dengan Pak Jay. Tapi, ia mengurungkan niatnya untuk menanyakan hal itu, sebab ia pikir itu bukan urusannya.
"Tolong sampaikan kepada Pak Jay kalau aku tidak bisa menerima semua ini. Dia hanya akan buang-buang waktu aja."
"Tapi, Utari... bukan kah kamu sedang mencari calon suami?"
"Ya, tapi mencari calon suami—orang yang akan hidup denganmu sampai akhir hayat—kan tidak semudah itu. Pilihan itu akan selalu ada, kan?"
"Jadi, Pak Jay tidak masuk dalam kriteriamu, Tar?"
"Bukan begitu. Bagaimana ya menjelaskannya... Perkara ini sesederhana aku tidak tertarik dengan beliau. Seperti ketika kau pergi ke sebuah mall dan melewatkan display pakaian karena memang kau tidak mau membelinya. Sesederhana itu, tidak ada alasan khusus."
"Kalau begitu, berarti kamu sudah punya incaran dong, Tari?"
"Mmm... bisa dibilang begitu." Utari terpaksa berbohong. Sirene memasang wajah sedih yang terlihat dibuat-buat. "Sayang sekali," katanya.
Saat Sirene sudah pergi, Utari tercenung melihat bunga mawar merah yang begitu angkuh menunjukkan kecantikannya. Bunga mawar pun tidak akan mengamuk karena disamakan dengan tahi kucing.
HARI sudah semakin sore. Azalea mengatakan pada Utari kalau ia ingin lembur di kantor untuk menyelesaikan beberapa laporan yang ditinggalkannya karena libur seharian kemarin. Biasanya, mereka pulang bersama dengan menumpang bus/kopaja. Terkadang, bila Johan menjemput Azalea dengan mobilnya, Utari diajak menebeng dan diantar sampai depan gang rumah.
Saat Utari hendak meninggalkan lobi gedung, ponselnya berdering. Azalea menelepon.
"Ya, kenapa, Za?"
"Utari, sebentar... Aku lupa kasih sesuatu. Tunggu di lobi, ya. Aku turun."
"Apa? Nggak bisa besok aja?"
Azalea sudah menutup teleponnya.
Sesuai dengan titah Azalea, Utari mengurungkan niatnya untuk segera pergi meninggalkan gedung. Ia duduk di salah satu sofa mewah dan super empuk yang ada di lobi. Orang-orang lalu-lalang masuk dan keluar gedung melewati lobi itu. Namun, lebih banyak yang keluar gedung karena ini sudah waktunya jam pulang kantor. Di seberang sofanya ada seorang anak laki-laki berseragam sekolah sedang sibuk menggores-goreskan pensil di atas buku sketsa. Utari memperhatikan anak itu. Semakin dilihat, wajah anak itu semakin familiar di ingatannya. Utari berusaha mengingat-ingat dimana ia pernah bertemu dengannya. Kemudian ia ingat mimpinya tempo hari, saat dua orang anak laki-laki menunjukkan ekspresi yang bertolak belakang di depannya.
"Apa anak ini ya yang hadir ke mimpiku waktu itu?" Tanya Utari dalam hati sambil terus mengamati anak itu.
Samar-samar, Utari melihat anak laki-laki itu sedang menggambar pemandangan kota—gedung-gedung bertingkat yang dilihat dari atas gedung. Setelah beberapa lama, anak laki-laki itu berhenti menggambar. Lalu, ia mengangkat kepalanya yang sedari tadi menunduk. Anak itu mengarahkan pandangannya ke mata Utari, kini mereka saling bertatapan. Seolah-olah ia merasa ada orang yang sedang memperhatikan gerak-geriknya.
Dua pasang mata mereka bertemu dan sepersekian detik kemudian, anak itu tersenyum padanya. Utari merasa dadanya tersentak. Ia ingat dimana pernah bertemu dengan anak itu. Di depan lift lantai 51, saat ia hendak pulang ke rumah. Utari membalas senyum anak itu, meski ia yakin agak sedikit terlambat.
Utari melihat anak kecil itu seperti mengucapkan sesuatu dengan lirih—ia tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya.
Seorang laki-laki datang mendekati anak kecil itu. Laki-laki yang sangat familiar bagi Utari. Dia adalah Pak Jay—yang langsung duduk di samping anak laki-laki itu.
"Sedang menggambar apa?" Tanya Pak Jay. Alih-alih menjawab pertanyaan Pak Jay, anak laki-laki itu malah menunjuk ke arah Utari. Perempuan itu salah tingkah saat Pak Jay melihat ke arahnya.
"Utari?" Panggil Pak Jay, alisnya naik. Utari tersenyum—dipaksakan—sambil menganggukkan kepalanya. Ia kaget setengah mati. Ternyata anak yang ada di depannya itu adalah anak Pak Jay. Anak yang melukis potret dirinya. Kali itu, mungkin untuk pertama kalinya Pak Jay menyapa Utari secara langsung.
"Jadi kalian sudah bertemu?" Kata Pak Jay. Anak itu berdiri dari duduknya, lalu menarik tangan Pak Jay dan memaksanya untuk mendekati Utari. Pak Jay berusaha menahannya, tapi ia juga sekaligus mengalah. Kini, Pak Jay dan anaknya berdiri hanya beberapa sentimeter dari tempat Utari duduk.
Tanpa mereka ketahui, jantung Utari berdetak dengan kencang. Tangannya bergetar dengan lembut—Utari menahan getaran itu. Udara di sekitarnya menjadi terasa panas, udara di dalam gedung perkantoran ber-AC itu. Utari tertunduk. Rasanya ia ingin meninggalkan lobi itu sekarang juga. Keningnya dan tengkuknya sudah bersimbah keringat. Azalea, cepat datang. Kata Utari dalam hati. Ia tidak pernah suka berada dalam situasi seperti ini.
"Utari, ini anak saya yang membuat lukisan yang pernah saya berikan ke kamu melalui Mbak Shiren." Kata Pak Jay. Utari mengangkat wajahnya. Saat itu ia melihat wajah Pak Jay yang keheranan.
"Kamu sedang sakit, Utari? Keringat dingin, ya?" Tanya Pak Jay.
"Ah, tidak kok, pak." Jawab Utari singkat sambil berusaha tersenyum. Anak Pak Jay tiba-tiba memegang tangan Utari. Hal itu membuat tubuh Utari kaku seketika. Anak itu masih tersenyum kepadanya, wajahnya sangat cerah. Seolah ada matahari di belakang kepalanya yang membuat anak itu terlihat sangat bersemangat, walaupun ia hanya diam saja.
"Benar tidak apa?" Tanya Pak Jay sekali lagi. Utari hanya mengangguk.
"Oh iya, kenalkan, Utari. Namanya Jaya Murcita. Tapi, teman-temannya biasa memanggilnya 'Jamur'" Pak Jay tertawa. Anak itu memegang telapak pergelangan tangan Utari dan mengangkat tangan Utari, lalu menurunkannya lagi. Anak Pak Jay melakukan gerakan itu berulang kali dengan cepat. Hal itu membuat Utari kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berdiri.
"Jay, tidak boleh begitu! Ayo lepaskan tangan tantenya." Agak aneh mendengar Pak Jay mengatakan namanya sendiri pada anaknya. Jay kecil atau Jamur langsung melepaskan tangan Utari. Ia lalu berlari menuju sofa tempatnya duduk tadi dan mengambil buku sketsanya dan memberikan kepada Utari. Ia membuka-buka beberapa halaman dan menunjukkannya pada Utari.
Pak Jay terpaku melihat pemandangan itu. Saat melihat apa yang digambar anak itu di dalam buku sketsanya, Utari merasa ketakutan sendiri. Pasalnya, hampir semua isi buku itu adalah gambar dirinya dengan berbagai pose. Bahkan banyak pose yang belum pernah ia lakukan saat sedang foto. Utari melirik heran ke arah Jamur.
Advertisement
- In Serial26 Chapters

Life Is But A Game
There are things everyone understands about life. It's chaotic, messy, and most of all, it doesn't give a damn about what you want or need. Even in a world that would be considered fictional, this idea still holds true. Dropped into a universe of demigods and incredible monsters, one young boy has to face the fact that his wants and needs matter even less than they did before. (Young Justice/DC Universe Gamer SI)
8 189 - In Serial145 Chapters

Aethernea
[Best Fantasy Story Winner at Wattpad Fiction Awards 2016] ? Adventure ? Mystery ? Humor ? Romance ? Systematic, almost scientific Magic ? Strategy in Fights ? Character Development Gallery | Wikia | Official Site | Patreon | Facebook | Twitter ————————————————————————————————————- Summary ————————————————————————————————————- In a world where everyone can use magic, where treasure hunters, alchemists, and warlocks are common professions, and where mage duels are the most popular form of entertainment, Kiel is a "non-mage" - a person who doesn't have the aptitude to use magic on regular basis - until he meets Elaru - a spell breaker of mysterious origin, wielder of the fabled 'Aethernea of Sight' - eyes that can see magic, who claims she can give him the power to become the greatest mage world of Halnea has ever seen. Coerced into binding his soul to hers, Kiel finds himself pulled into a web of secrets, where one wrong step could end in his untimely demise. Who, or what is Elaru Wayvin really? What is her relation to the ruling 15 noble mage families? What is the source of The Ink - a mysterious plague spreading through the continent? What is the Aetherneal bond between them and what has it turned them into? What is the truth behind gods and divine magic? Why has the third race of Halnea - the Ascended, mysteriously disappeared, and what is the connection between the remaining two races? In the search for truth, Kiel and Elaru enroll at the most prestigious University of Magic. Yet, between awkward social events, falling in love, thrilling competitions, blood curling battles, irritating peers, and damnable love rivals, there is little time for studying. And as if avoiding sinister plots from all sides wasn't difficult enough, their new detestable mentor takes them on a voyage into the uncharted forbidden zone filled with unspeakable secrets, ancient riddles, man-eating monsters, and deadly traps. A quest that just might end up changing the fate of the entire world. ————————————————————————————————————- What do readers say about it? ————————————————————————————————————- "Aethernea is my absolute favorite read on wattpad, I love it as much as I love Harry Potter and The Mortal Instruments. You have such an amazing way to make the words flow and unbelievable descriptions. Unique characters and a great story line. All the small clues and mystery in the humor and fantasy just makes the book perfect in my opinion. I read all chapters in two days! Less than 48 hours even! I'm REALLY looking forward to the next update, the world of Aethernea is so deep and well thought out, it's beautiful and magical. God I can't believe how creative you are, so many small details with so many families and stories everywhere. Purely fantastical, I admire you." - astro-logical from Wattpad "I love love love Aethernea so much! It is amazing how you created this new world with different creatures, magics, looks, illnesses, and evil! I was blown away by your explanation of the Mana pools and how to weave magic! Simply stunning really! You are one of my favorite authors and Wattpad and I am so glad I stumbled upon Aethernea because it is worth all of my time reading!" - Adriana_V_Blade from Wattpad "I absolutely am loving Aethernea so far. I am certain you belong in the ranks among J.K. Rowling, Rick Riordan, Suzane Collinings, and many more great and wonderful authors. You opened up a whole new world for me, which only a few great authors have accomplished. While it's true I am pulled into each and every book, few are able to capture me to the point of inescapability. Though, somehow, you have managed this feat. I thank you for this and more! You are a wonderful author and can't wait for more to come!" - daughterofpercabeth7 from Wattpad "WOW! just caught Aethernea in gravity tales! Just when I was getting tired of most xianxia novels this appears and completely blows my mind! I really like the depth and the humorous touch you give the characters and it seems you have the storyline well thought out since you are always hinting about things in the past and the future. It has been such an enjoyable experience that I couldn't stop reading, finishing it in just one day and laughing my way through most of the episodes. But what keeps me so excited for what's coming is the magic system and the professions of the world you are creating.The magic mechanics have such a huge potential! They are simple but at the same time they open so many possibilities. Even though we still only understand the basics of transmutation and augmentation, I expect them to enable fights where there is need of quick thinking and skill, and not just brainless overpower of every opponent. In a way this makes me reminiscent about The Mistborn Series by Brandon Sanderson, which are one of my favorite series ever. The thing that sets Mistborn apart from any other series is that the mechanics are so well thought out that they could be used to create a super cool triple A video game and I cannot help but hope Aethernea reaches the same level or even surpass it. I really think it has that potential. Really hope this series gets the attention it deserves. As for me, Thursdays and Sundays just got a whole more exciting! =)" - AlexMLion "Your writing is fantastic and riveting, the chapters and character flow so smooth, and it captivates the reader with the many twist and turns that tricks one mind into thinking this is about to happen, when suddenly the exact opposite happens. You truly are in inspirational writer with a brilliant mind that can see and put words into chapters and into this one truly awesome book. Thank you!" - AshleyStaar from Wattpad "I loved this story, such detailed description and accurate words, both Kiel and Elaru completely caught my attention, your writing style is just beautiful and the plot is astounding and it's just the first episode! This kind of fantasy stories are my favourite, it has a lot of magic in it, rivalry and sense of humour." - BlackWhiteD from Wattpad
8 73 - In Serial10 Chapters

Farming Heroes and Villains to become Immortal
I jinxed myself and was hit by a truck. When I thought that it was all over and i would be sent to enjoy the afterlife I was told that i was going to the Reincarnation Well to live a new life. Even that was denied from me as I accidently transmigrated to the immortal realm. Join me as I farm the vilains and sons of destiny to become immortal.
8 194 - In Serial10 Chapters

Sons of God, Daughters of Men
Locked deep in the mind of Analise Crawford is the location of the last piece of the map to the Gates to Hell and the key to unlocking it. Five years ago, to protect this secret, she injected herself with a serum to erase her memories. She remembers nothing of her decree to protect humanity from the darkness, nor that The Firm, a secret cartel of demon loyalists, has been sent on a mission to collect her. However, vivid dreams of shadowy men, broken stone tablets, and strange encounters with familiar, but unrecognizable, faces awaken her curiosity and set off her paranoia.When a clandestine Firm tracker locates Analise her estranged family intercepts, bringing her back to a vicious power struggle between light and dark. As Analise slowly regains fragments of her memories, she tries to piece together answers to the two big questions: Where is the last piece of the map, and why am I charged with protecting it? In the meantime, The Firm is closing in on a source of leverage, a still forgotten secret—her daughter.
8 120 - In Serial53 Chapters

Quick Transmigration : System Let's Take Revenge
𒆜 Oᑎ-GOIᑎG 𒆜System: Host you just need to take revenge on the FLand complete task and your mission will be a success.Liza: Just these come on let's do it. ~~~~~after completing some worlds~~~~~Liza: system chan~~ How the hell is this demon following me everywhere like a curse ?!System: ..he..he..he.......congratulations host you have successfully completed the hidden mission .😊😊Liza: Abort mission I won't do it .A certain person: Since you have entered my heart don't you dare think of running.●○•° 《 Extremely slow updates😥 so please🥺 be patience 》°•○●
8 200 - In Serial34 Chapters

Goblin Cave
[Goblin Cave] is a perfectly average Dungeon that becomes unsatisfied with its work.
8 71







 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl