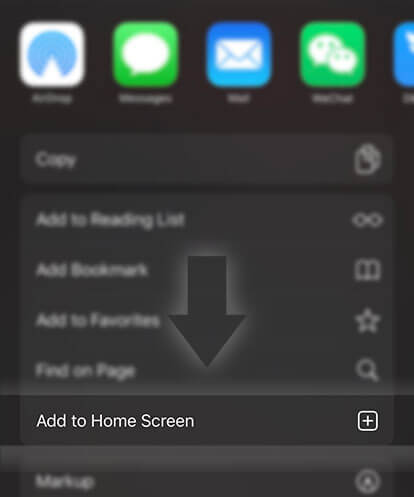《UTARI》Bab 6 - Cerita Laras
Advertisement
SETIAP pagi, Utari akan menemukan segelas kopi yang di gelasnya tertempel note kecil dari Pak Jay. Kebanyakan note itu tertuliskan kata-kata penyemangat dan kutipan-kutipan dari lirik lagu atau buku-buku.
"What you seek is seeking you – Rumi." Begitu kata-kata yang tertulis di note yang tertempel di gelas kopi styrofoam dari Pak Jay. Utari mengangkat gelas itu dan membaca kalimatnya sekali lagi.
"Pagi, Utari! Selamat meminum kopi." Tiba-tiba Sirene muncul di belakangnya, membuat Utari tersentak. Ia meletakkan gelas kopi itu dan membalikkan badannya ke arah Sirene.
"Santai saja. Aku cuma mau memberikan titipan dari Pak Jay untuk kamu, Tari." Perempuan itu menyodorkan sebuah bingkisan berupa kotak yang cukup besar dibalut kertas kado berwana merah jambu.
"Apa ini?" Utari menatap mata Sirene, tanpa menyentuh bingkisan itu.
"Mana aku tahu. Aku cuma diminta memberikannya ke kamu."
"Aduh maaf, Shiren. Tapi, aku nggak bisa menerima ini. Aku sedang tidak ulang tahun." Tolak Utari. Sebenarnya ia penasaran juga hal apa yang membuat Sirene sebegitu gencarnya membantu Pak Jay untuk mendekatinya. Tapi, walaupun hari itu ulang tahunnya pun, bukan berarti ia akan menerima kado pemberian Pak Jay begitu saja.
"Utari sayang, ini bukan hadiah ulang tahun. Ini kado dari Pak Jay untuk kamu." Nada bicara Sirene dibuat-buat dan Utari tidak terlalu senang mendengarnya. Ia lalu menyodor-nyodorkan bingkisan itu ke tubuh Utari. Azalea menatap mereka dari mejanya dan memberikan isyarat kepada Utari untuk menerimanya saja.
"Hhh... Shiren, kamu ini kenapa hobi sekali memaksa, sih?" Kata Utari jengkel.
"Aku hanya menjalankan amanah dari Pak Jay, Utari. Terima ini!" Kata Sirene setengah memaksa sambil mengambil kedua tangan Utari dan meletakkan bingkisan itu di sana.
"Ini karena kamu memaksa, ya." Tegas Utari. Semestinya Sirene tahu kalau maksud perkataannya barusan kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan pemberian-pemberian Pak Jay—termasuk juga dengan Pak Jay-nya.
"Sama-sama, Utari." Sirene tiba-tiba berkata demikian, padahal Utari tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Mungkin ingin menyindir Utari yang dianggapnya tidak tahu terima kasih karena telah diberikan sesuatu oleh -orang lain. Apalagi, benda yang diterimanya itu ternyata tidak ringan. Utari mulai menerka-nerka apa isinya. Tapi, ia tidak ingin membuka bingkisan itu sekarang.
Sirene melangkah pergi meninggalkan Utari. Dari tempatnya, Utari dapat mendengar Sirene yang sedang terkekeh. Utari mulai curiga kalau Sirene hanya ingin cari muka di depan Pak Jay agar dapat direkomendasikan untuk promosi jabatan. Pak Jay, atasan Sirene, bukan lah orang yang banyak bicara dan pembawaannya terkesan kaku. Utari tidak tahu bagaimana ceritanya Sirene bisa dekat dengan Pak Jay dan mau membantu atasannya itu sebagai kurir pengantar paket "PDKT". Meskipun begitu, Utari tidak heran karena perempuan yang usianya tidak lebih tua darinya itu terkenal suka "menjilat" orang. Maka, terkadang teman-temannya di kantor saat sedang berbisik-bisik membicarakan Sirene sering menyebutnya "ular" dan begitu lah Utari belajar mengenai bagaimana tabiat seseorang dinilai oleh orang lain. Ada lebih banyak hal yang tidak kita ketahui dibanding apa yang kita ketahui. Sebab dunia yang kita kenal tidak lebih dari seluas pandangan mata kita saja.
Utari telah membuka buku catatan kecilnya yang berwarna merah marun. Tak ada catatan tambahan mengenai Pak Jay. Ia telah berulang kali melakukan ritual memanggil suara-suara yang akan memberikannya informasi mengenai laki-laki yang mencoba mendekatinya. Namun, yang ia rasakan hanyalah keheningan yang dalam. Usai melakukan ritual itu, biasanya Utari akan mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Tadi malam ia bermimpi bertemu dengan anak kecil, kira-kira usianya sekitar 10 tahun. Ada dua orang anak kecil. Yang satu berwajah ceria, dan satunya lagi wajahnya tanpa ekspresi secara bergantian. Kedua anak kecil itu tidak melakukan apapun, mereka hanya menampakkan dirinya di hadapan Utari. Lalu, saat bangun kepalanya menjadi sangat berat.
Advertisement
Hujan mengguyur ibu kota dengan ganas di awal Februari. Hujan malam itu berbeda dari hujan-hujan biasanya. Bila hujan adalah manusia, mungkin titik-titik hujan yang jatuh ke tanah ibu kota yang turun dari langit kemarin malam sedang kegirangan. Pasalnya, kali ini kedatangan mereka begitu ditunggu-tunggu dan membuat sebagian orang yang ada di negeri ini mengucap syukur yang tak habis-habis kepada Yang Maha Kuasa. Hujan sering kali diabaikan, bahkan sering pula dicaci maki karena dituding jadi penyebab utama "tenggelamnya" kota. Berbeda dari biasanya, hari itu hujan disambut dengan lebih gegap gempita. Mereka berbaur dengan warna merah terang, naga-naga, dupa, dan doa.
Meja Azalea kosong. Hari itu ia libur dan berencana pergi ke wihara bersama dengan seluruh keluarganya. Kantor terlihat lebih "merah". Berbagai properti imlek dipasang secara sederhana di ruangan yang cukup luas itu. Celetukan tentang "angpau" dan "barongsai" sesekali terdengar di ruangan itu. Hari itu, Utari tidak bisa tidak mengenang Abimanyu. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana ia merayakan Hari Raya Imlek tahun ini. Bila lelaki itu masih berada di dekatnya, ia pasti sudah mengajak Utari melihat kembang api dan pertunjukan barongsai di Taman Mini. Lalu, menghadiahkannya satu plastik kue keranjang yang merupakan salah satu makanan favoritnya setelah Abimanyu memberikannya saat Imlek bertahun-tahun silam.
"Utari, apa kabar kamu? Hari minggu kita jadi bertemu, kan?" Aksara mengiriminya pesan lagi via SMS.
"Insya Allah. Sejauh ini belum ada perbuhanan rencana. Memang kenapa?" Balas Utari.
"Tidak apa. Ingin memastikan saja. Sudah dapat berapa angpau? :p" Canda Aksara. Baru pertama kali lelaki itu mencoba bercanda dengan Utari."
"Lumayan. Tapi, seharusnya bisa lebih banyak." Entah apa yang ditulis Utari di SMS balasan itu. Ia sedang tidak ingin bercanda. Seharian ini, pikirannya sedang diusik oleh masa lalu bernama Abimanyu. Hal seperti ini tidak pernah terasa sederhana bagi Utari.
SORE harinya, Utari menerima pesan dari Laras. Adiknya meminta bertemu di Pasar Festival selepas jam kantor. Utari bertanya mengapa mereka tidak bertemu saja di rumah dan membicarakan apapun yang ingin dibicarakan saat makan malam. Laras menjelaskan kalau ia lebih suka mengobrol di luar agar tidak ada yang mengganggu pembicaraan mereka.
Malam itu, mereka akan izin untuk tidak ikut makan malam bersama pada ibu. Utari menuruti sambil dalam hati bertanya-tanya apa yang hendak dibicarakan oleh Laras. Tentu saja, hal pertama yang terlintas di kepalanya tentang apa yang ingin dibicarakan adiknya itu adalah tentang rencana pernikahannya dengan Ridwan. Hal itu semakin jarang dibahas di rumah. Ibu mungkin sudah tidak peduli lagi, begitu juga dengan Utari yang dengan keras hati mengabaikannya. Hubungannya dengan Laras juga berubah semenjak sebulan yang lalu, setidaknya itu yang dirasakan Utari. Adiknya itu sering kali terlihat menghindarinya. Utari paham mengapa Laras bersikap seperti itu, meskipun sebenarnya Utari tidak menghendaki keadaan seperti itu terjadi antara dirinya dan adiknya. Bukan ia penyebabnya, tapi Utari tetap merasa bersalah.
Hal ini juga pernah dilakukan oleh Ratri dulu. Adiknya yang pertama itu pasti sudah tahu tentang kabar ini dari ibu atau dari Laras, dan ia akan merasa iba sehingga tidak ada alasan baginya untuk menghubungi dan menanyakan kabar Utari. Mungkin Ratri takut kalau kemunculannya hanya akan membuat Utari bertambah kegundahannya. Seberapapun Utari menyangkalnya, ia tahu kalau beban di pundaknya kini bertambah.
Dari ketiga adiknya, Laras mungkin adalah adik yang paling tidak dikenal oleh Utari. Mereka tidak pernah duduk berdua saja sambil bercerita secara mendalam. Tidak seperti yang sering dilakukannya dengan Ratri dan Utami. Yang ia paham tentang Laras, dia adalah gadis yang pemberani dan banyak diidolakan oleh laki-laki. Pernah suatu kali saat Laras menunggu Bus di halte dekat rumah bersama dengan ibu dan Utari, ia melihat seorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah halte itu merokok. Asapnya disembur seenak jidat ke udara, orang-orang disampingnya tutup-tutup hidung sambil batuk-batuk. Laras, sejak pertama kali berdiri di halte itu memperhatikan laki-laki berbadan tambun yang sedang merokok itu. Utari memperhatikan adiknya itu. Tatapannya—Laras—tajam, seperti ingin membunuh. Lalu, ia berjalan ke depan laki-laki itu untuk menegurnya. Laki-laki itu tidak menghiraukannya. Ditegurnya sekali lagi, laki-laki itu malah memelototinya.
Advertisement
Bukannya kembali ke pelukan ibu, Laras mengambil batang rokok yang sedang menempel di bibir laki-laki itu dengan paksa. "Maaf, asap rokok bapak mengganggu banyak orang di sini."
Ibu segera menghampiri Laras dan meminta maaf atas perilaku anaknya itu kepada laki-laki tadi. Lelaki itu pergi sambil memaki Laras dan ibu.
Laras balas berteriak, "bapak, raja setan!" Saat itu usia Laras baru 16 tahun. Seumuran dengan Utami, saat ini.
LARAS telah duduk di salah satu bangku yang ada di depan kaca jendela sebuah restoran di Pasar Festival dengan satu mug cokelat panas di depannya dan segelas cappuccino. "Ini buat mbak?" Tanya Utari begitu sampai di meja Laras.
"Iya. Serenteng cappuccino sachet di dapur itu punya mbak, kan? Aku ingat."
Utari tersenyum. Laras bahkan ingat kopi kesukaannya. Tapi, hal itu rupanya tidak berlaku sebaliknya.
Mereka duduk berhadapan. Utari menyandarkan punggungnya. "Jadi, apa yang sebenarnya mau kamu bicarakan, Ras? Tumben sekali sampai mengajak bertemu di luar rumah begini."
"Mbak merasa nggak sih kalau di rumah kita itu ruang privasinya sedikit sekali. Sekamar aja ada dua penghuni."
"Iya, tapi biasanya juga nggak ada masalah kan." Utari menyeruput cappuccino-nya. "Atau kamu mau cerita tentang suatu rahasia ya?"
Wajah Laras berubah. Utari bergidik tiba-tiba.
"Tapi aku bingung, mbak, mau memulainya dari mana."
"Boleh mbak menebak, Ras?" Laras mengangkat kedua alisnya. "Ini ada hubungannya dengan rencana pernikahan kamu?"
"Iya, mbak. Sebenarnya aku ingin mbak tahu alasan kenapa aku bersikukuh untuk menikah dengan Ridwan. Pasti mbak bertanya-tanya, kan. Kenapa aku mau menuruti keinginan Ridwan untuk menikah buru-buru? "
"Karena Ridwan ingin pergi ke Rusia akhir tahun ini dan ia meminta kamu menemaninya di sana. Begitu?"
"Iya. Memang benar begitu, mbak. Tapi, sebenarnya ada alasan lain yang lebih penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Alasan yang membuat aku tidak ingin lepas dari Ridwan. Selamanya tidak ingin."
"Bukankah semua orang yang sedang mabuk cinta akan merasakan hal seperti itu, ya?" Utari menyeruput cappuccino-nya lagi.
"Iya, mbak. Itu juga benar. Mungkin aku sudah terlalu jauh mencintai Ridwan sampai begitu ingin menuruti keinginannya." Laras menunduk. Air mukanya berubah. Utari mempehatikan bibir Laras sedikit bergetar. Ia tak dapat mencegah sebuah terkaan muncul di kepalanya saat itu.
"Kamu...?" Utari tidak meneruskan ucapannya karena baginya hal itu akan terdengar sangat mengerikan. Namun, Laras sepertinya mengerti kalimat apa yang akan dikatakan kakaknya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya lemah. Utari merasa lega.
"Untungnya tidak sampai...." Laras memberi jeda, "hamil."
"Maksud kamu?"
Laras tidak menjawabnya. Kepalanya menunduk dan tangannya sibuk meremas-remas serbet yang ada di depannya. Sesaat kemudian, Utari ingat kejadian saat Laras menegur perokok di halte dan saat ia diskors karena berani membuat perhitungan dengan guru olahraga yang pernah menendang pantat temannya karena dinilai tidak becus melakukan lompat kuda, padahal anak itu laki-laki. Atau pada saat ia kabur dari rumah setelah bapak—yang jarang marah itu—memukulnya karena ia ketahuan bolos dari sekolah.
Kemudian, ia mulai menangis. "Mbak, kali ini aku salah, mbak. Tapi, aku mohon jangan bilang ibu. Aku takut kehilangan semuanya."
Ada perasaan campur aduk di dalam diri Utari. Marah sekaligus iba. Tapi, mungkin lebih tepat kalau disebut kecewa. Sebutir air mata jatuh dari mata kirinya. Bagaimana bisa ia tahan melihat adiknya sendiri merasa hancur seperti itu. Bukankah perempuan manapun akan merasa hancur kalau apa yang seharusnya dijaga hingga sebuah janji terucap itu terampas belum pada waktunya. Tapi, ia dengar sekarang kepercayaan seperti itu sudah tidak populer dianut oleh perempuan di negeri ini. Jadi, mungkin saja ia salah.
"Ridwan itu sepertinya lelaki brengsek, ya. Sudah memerawani kamu, sekarang dia tega menjadikan kamu pilihan. Kamu yakin mau menikah dengan dia?" Kata Utari kesal. Ia menghela napas panjang.
"Ridwan itu lelaki yang baik, mbak. Dia hanya tidak percaya dengan dirinya sendiri. Menurutku alasannya wajar. Banyak pasangan yang hubungannya kandas karena terpisah jarak yang jauh. Banyak alasannya. Aku sendiri juga takut." Laras melanjutkan, "Itu alasan pertama. Alasan kedua, aku nggak ingin menikah dengan orang selain Ridwan karena hal yang aku ceritakan sebelumnya. Tidak satu orang pun, mbak. Kalau pun Ridwan pada akhirnya memilih untuk melepaskanku, aku lebih baik tidak usah menikah seumur hidup. Aku tidak melebih-lebihkan, mbak. Perasaan bersalah kepada diri sendiri ini rasanya hendak membunuhku."
Utari mendengus ketika Laras menjadikan cinta sebagai alasan utamanya. Tapi, ia juga tidak sampai hati kalau memaksa adiknya menjauhi Ridwan karena sama saja membiarkan lelaki itu lari dari tanggung jawabnya. Lagipula hal seperti itu sepertinya mustahil dilakukan oleh Laras yang keras kepala. Utari kemudian sadar betapa besar harga yang harus dibayar oleh seorang perempuan ketika ia memutuskan untuk melepaskan keperawanannya diluar pernikahan. Diperas, dibuang, dikucilkan, bahkan dirajam sampai mati.
Utari menatap Laras lama. Dahinya berkerut, mengguratkan kekecewaan. Ia paham maksud Laras membagi rahasia ini kepadanya. Ia menemukan sebuah paradoks. Dimana ia menganggap hal yang dilakukan oleh Utari adalah sesuatu yang konyol, tapi sekaligus tak dapat begitu saja diabaikannya.
"Mbak, mau kan bantu Laras meluluhkan hati ibu?" Kata Laras setengah memohon sambil memegang tangan kakaknya.
Utari memandang Laras, semestinya ia tahu ini bukan perkara mudah. Tapi, ia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk, meskipun belum tahu apa yang akan dilakukannya. Mungkin, ia bisa berpura-pura mengenalkan seorang laki-laki kepada ibunya seperti yang pernah dilakukan Utari dulu.
Tangisan Laras semakin menjadi. Laras pasti begitu ketakutan sampai rela menceritakan rahasia ini kepadanya. Ia sudah kehilangan banyak, dan tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi dengan melepaskann Ridwan. Sekarang Utari bingung, sebenarnya kesendiriannya ini masalah siapa. Mengapa untuk menyelamatkan hidup orang lain—yang sebenarnya adalah saudaranya sendiri, ia harus mengorbankan diri sendiri. Tapi, dipaksa untuk segera menemukan calon pasangan hidup, apakah juga berarti perngorbanan? Rasanya tidak. Sebab di dalam hati, Utari sebenarnya sudah merindukan lelaki itu, yang entah siapa.
"Mbak, itu kado dari siapa? Besar sekali." Tanya Laras saat mereka hendak beranjak.
"Mbak juga nggak tahu. Yuk, kita pulang!"
"Masa nggak tahu dari siapa?"
"Eh, maksudnya mbak nggak tahu isinya apa. Dari siapanya, adalah."
Laras tersenyum sambil melirik Utari.
Advertisement
- In Serial46 Chapters

Prehistoric Barbarian
The future became a peaceful utopia in the Core Regions. No crime, no wars, no conflicts, even rude behavior is rare. People became complacent and lazy. The main character isn’t a hero or a typical protagonist. Calling him an… opportunist would be the least offensive probably. In this age, he’s sticking out like a sore thumb. Who would notice a few shady happenings when crime is a foreign concept and there is nobody to catch you? *Book 1 - Done.*
8 198 - In Serial25 Chapters

Extra Professor
A man who has nothing, freedom chained, and happinness unsought. An empty void. Rio, a part time editor of a novel called The Last Stand. Transmigrated inside the novel as a professor. A professor that was not even mentioned in the story. He was an extra that had no part in any events. Armed with the advanced knowledge of the future, he will do whatever it takes to survive in the world of gruesome fantasy. However, is surviving really his goal?
8 319 - In Serial12 Chapters

The Dragonfly - Chronicles of Edalom
The fur tournament is approaching and the little kings are mobilizing to get a good piece to present. Derren, hunter of the Thousand Kingdoms, accepts a job for three thousand silver shields. With his saber on his back, he sets out with other hunters in search of the dragonfly, a monster described only by rumors.
8 156 - In Serial9 Chapters

Witch's Law
What's the secret of a girl who dreams of revenge on her father and stepmother? Dazzling beauty Soojin's sudden move to japan, her rise to stardom, and the unraveling of a three generation long family secret.
8 129 - In Serial13 Chapters
Logius Code
A hermitic god, betrayed by the Realm of Deities and its denizens for his past, and framed for interfering with the mortal realm, is cast into the oblivion that begets creation: The Exodus, the dark portal from whence all the gods originate. If this wasn't a tragedy by itself, what came next certainly was. Through the Exodus, his spirit is ejected from its depths, and into the world he risked his safety for; into the body of a mortal no less. Can Dorusc the Aloof, the fallen god, regain his divine power to avenge himself, and bring the all-powerful Majestic, Lord of the Deities and mastermind behind the world's coming destruction, to his knees? Or will he lose himself to the impending darkness that threatens the world he finds himself in, perishing before learning the true reason it was chosen for ruin?
8 72 - In Serial32 Chapters

My Luna, Helena.
*• POV IS IN BOTH MALE AND FEMALE•*•• Any similarity to a different story is a complete coincidence! I thought of this story on my own.••18 year old Helena Celine was known for her beauty and kindness, but also known for being abused and alone. She's always been different for having white hair and vibrant purple eyes.Her family has rejected her completely and everyone's labeled her as the outcast. Her 2 older brothers contribute to the beatings while her father and mother stand by and watch.Alpha Levi is aware of the way his pack treats Helena but he takes no actions to stop her torture. In fact, he joins in every one and a while to make the poor girl more miserable and broken.When they clash on Helena's 18th birthday he knows right away he needs to reject her. To him she's incapable of running a pack, especially when that pack hates her.Lucky for Helena, she takes the rejection quite good and is able to find the strength inside of her to get out and move on to something better.--I SUCK AT DESCRIPTIONS IM SO SORRY!!!
8 144

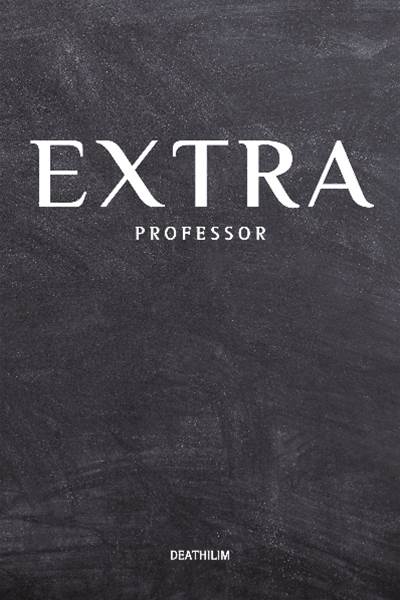




 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl