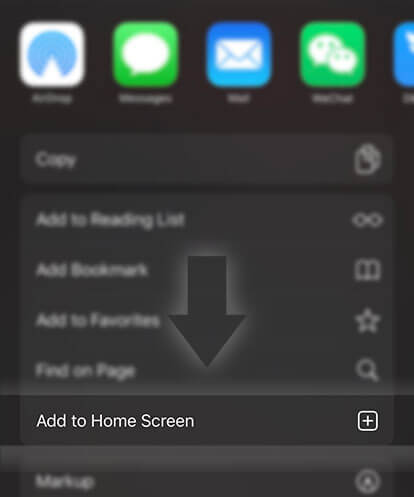《UTARI》Bab 3 - Permintaan Kedua
Advertisement
UTARI mengenal Aksara sejak masih duduk di bangku kuliah. Mereka hanya sering bertemu di stasiun kereta atau di dalam kereta listrik saat hendak pergi ke kampus. Saat itu, satu kali pun mereka tidak pernah bertegur sapa. Aksara yang sekarang, bagi Utari, terlihat berbeda dengan aksara yang dulu. Perkenalan mereka berdua terjadi secara tidak sengaja. Saat itu Utari berdiri di dalam kereta, menghadap ke jendela. Ia berdiri tepat di depan seorang laki-laki yang sedang tertidur. Selama berada di dalam kereta, Utari berpegangan pada gagang yang menjuntai dari tiang-tiang dekat tempat menaruh barang yang ada di atas bangku.
Sesuatu telah terjadi hari itu dan sejak kereta yang sedang ditumpanginya itu datang di stasiun tempatnya menunggu, Utari menahan rasa sesak. Ia mencoba menahan getaran yang muncul dari dalam dadanya, yang menjalar ke matanya. Pertahanan Utari roboh. Air mata menetes dari matanya dan terjatuh mengenai punggung tangan lelaki yang duduk sambil tertidur, tepat di depannya. Air mata itu membangunkan lelaki yang ternyata adalah Aksara. Saat itulah, untuk pertama kalinya Utari melihat senyuman Aksara. Senyuman yang menenangkan hati.
Ibu, Laras, dan Utami ribut menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya selama prosesi pernikahan Seno dan Maya saat perjalanan pulang ke rumah. "Itu sepupunya Maya. Namanya Aksara. Dia dulu teman aku di kampus, bu. Aku nggak menyangka akan ketemu dia di pernikahannya Mas Seno—apalagi, menyangka kalau dia adalah sepupunya Maya. Karena sudah lama tidak mengobrol, ya sudah, kami puas-puasin mengobrol tadi."
"Serius cuma sebatas itu, mbak?" Tanya Larasati.
"Iya, cuma sebatas teman." Jawab Utari santai.
"Mbak yakin? Tapi, sepertinya Mas Aksara itu suka sama mbak. Buktinya, aku perhatikan, dia mengikuti mbak terus selama acara. Seperti ekor anjing yang yang sedang kenyang. Kalau tidak diperhatikan dengan seksama, nggak akan ngeh." Sela Utami.
"Utami, nggak boleh seperti itu. Masa' orang disamakan dengan ekor anjing." Tegur ibu yang duduk di bangku depan. "Utari, tapi nggak ada salahnya mendengarkan perkataan adikmu itu. Kalau Aksara suka sama kamu, mbok ya dicoba dulu. Jangan selalu menghindar. Ibu ini sudah menyerah rasanya, nduk. Seno, laki-laki, yang seumuran denganmu saja sudah berani menikah. Masa' kamu, perempuan, hari gini belum menikah juga. Untung tadi ada Nak Aksara."
"Wes... Biarkan saja, toh. Kalau Aksara itu jodohnya Utari. Dia juga nggak akan menghindar. Jadi, tenang saja nggak usah terlalu dipikiran begitu, Utari." Mungkin Om Rusli melihat perubahan ekspresi wajah Utari saat mendengar perkataan ibunya dari kaca spion dalam mobilnya.
Utari tidak menjawab. Ia membuang pandangannya ke luar jendela. Langit mulai gelap, namun warnanya tidak jernih. Senja yang berwarna kejinggaan itu sebagian besar tertutup awan kelabu. Semakin kencang mobil itu melaju, semakin pekat gumpalan asap abu-abu yang berada di langit. "Hujan lagi," batin Utari saat tetesan air hujan jatuh di kaca jendela mobil itu.
PERTEMUAN selalu menjanjikan perpisahan, begitu pikir Utari. Aksara, laki-laki yang terakhir ditemuinya di pernikahan Seno dan Maya hampir tiga bulan yang lalu itu menghilang. Seolah awan kelabu yang dilihatnya saat perjalanan pulang dari resepsi pernikahan tempo hari adalah tanda. Utari membayangkan awan kelabu itu menyelubungi lubang terang dari langit. Lubang itu menghisap siapa saja yang diinginkannya—manusia-manusia yang terhisap itu tidak dipilih secara acak, tapi Utari tidak tahu kriteria apa yang membuat mereka bisa terhisap atau terpilih untuk diangkat kelangit dan menghilang selama-lamanya dari muka bumi. Awan kelabu pekat yang serupa dengan yang dilihatnya bertahun-tahun yang lalu, Enam atau tujuh tahun yang lalu. Awan itu memenuhi janji yang diucapkan sebuah pertemuan, mengabulkan perpisahan.
MALAM tahun baru, 31 Desember 2000.
Menjelang pukul tujuh malam itu, ibu dibantu dengan Utari menyiapkan piring, gelas, air minum dan makanan yang dimasak ibu tadi pagi—yang telah dihangatkan—di meja makan. Biasanya Utami yang bertugas membantu ibu. Tapi, Gadis berusia 15 tahun itu baru sampai rumah setengah jam yang lalu dengan wajah ditekuk dan tubuh yang lemas. Ia mengeluarkan sampur jumputnya yang berwarna merah, strapless, kipas, kaos dan legging dari dalam tas, lalu merebahkan tubuhnya diatas sofa di depan TV. Ibu bertanya mengapa wajahnya seperti itu, tapi Utami hanya menjawab, "nggak pa-pa, bu." Tapi, wajahnya malah kelihatan lebih tegang.
Advertisement
Mereka berkumpul di meja makan hampir setiap malam. Bapak dan ibu membiasakan mereka untuk setidaknya sekali waktu dalam sehari berkumpul untuk berinteraksi. Bapak yang mengusulkan ide ini pada ibu, jauh sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Saat mereka berbincang sambil makan bakso langganan di Ancol, di malam minggu yang basah oleh gerimis yang romantis. Ibu tersipu ketika bapak mengatakan bayangannya kalau mereka berkeluarga. Anak enam, rumah dengan halaman luas yang asri, mereka harus selalu makan malam bersama, rumah yang cukup luas untuk mereka tempati ber-delapan. Semuanya disanggupi ibu saat itu, sebab ia sedang mabuk kepayang karena katanya laki-laki yang mau membagi rencana masa depannya dengan seorang perempuan, berarti adalah laki-laki yang menjalani hubungan dengan serius.
Pada kenyataannya, ibu dan bapak harus puas dengan empat anak—seharusnya lima, tetapi jabang bayi pertama itu meninggal dunia sebelum berhasil melihat dunia karena terbelit tali pusar saat masih di dalam perut ibu. Kenyataannya lagi, mereka harus puas tinggal di rumah sederhana tanpa pekarangan yang luas di dalam suatu gang di Kota Jakarta yang mulai padat penduduk. Dari tahun ke tahun semakin banyak penduduk yang pindah ke Jakarta. Pembangunan yang masif dilakukan oleh pemerintah seolah memberikan janji baru pada masyarakat yang tinggal di desa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan. Hal itu pula yang mendorong bapak pindah ke Jakarta, meskipun kenyataannya ia hanya bekerja sebagai buruh yang pindah dari satu pabrik ke pabrik lainnya. Sering kali mengeluh soal bayaran yang tidak sesuai. Bapak pernah sekali ikut aksi yang dimotori oleh salah seorang temannya untuk menuntut keadilan di depan istana kepresidenan. Saat itu, ia merasa cukup terpukul dengan kematian salah seorang temannya, Parman, yang bunuh diri akibat tidak tahan dengan tekanan yang diterimanya di tempat kerja.
Bapak meninggal saat Utami, adik Utari yang paling kecil masih berusia 10 tahun. Tak lama setelah ia memutuskan untuk keluar dari pabrik dan memulai wirausaha dengan membuka bengkel sepeda motor di depan gang rumahnya. Bapak meninggal karena kanker paru-paru akibat terlalu sering mengonsumsi rokok. Semenjak saat itu, Laras, adik Utari yang nomor dua sangat membenci rokok. Ia yang paling terpukul atas kematian bapak. Sejak dulu, Laras adalah anak yang paling dekat dengan bapak dibandingkan dengan anak-anak lainnya.
"Laras kemana?" Tanya ibu. Makan malam mereka tidak akan dimulai sebelum semua anggota keluarga belum berkumpul. Ibu berteriak memanggil Laras, namun tak digubris. Utari beranjak dari bangkunya untuk menghampiri Laras ke kamarnya, di lantai dua.
"Laras, ayo turun. Sudah ditunggu ibu." Kata Utari sambil mengetuk pintu kamarnya.
"Iya, mbak sebentar." Jawab Laras dari dalam kamar. Suaranya terdengar parau.
"Jangan lama-lama!" Utari kembali ke meja makan, sementara Laras masih berkutat dengan urusan-yang-entah-apa di dalam kamarnya.
Laras tiba di meja makan dengan membawa "hawa dingin". Tidak seperti biasanya, ia terlihat tidak bersemangat. Seperti ada sesuatu yang menggelendoti pundaknya yang turun dan mencekat di tenggorokkannya. Ia terlihat tegang. Sementara itu, Utami duduk dengan lesu dan kepalanya menunduk seperti orang yang baru saja melakukan kesalahan. Ibu dan Utari memperhatikan mereka dengan tidak kentara, membiarkan apa yang anak-anaknya bawa ke meja makan itu mengendap. Kalau ada bapak, Utari tidak akan khawatir karena ia tahu bapak akan bertanya dan kedua adiknya itu akan menjawabnya dengan jujur meski dengan sangat hati-hati. Ibu sengaja berdeham ketika mengambilkan nasi dan lauk pauk ke piringnya. Utari melirik Laras dan Utami yang masih saja menunduk, bibirnya masih terkatup rapat.
"Kalian mau makan apa mau manyun saja sampai kelaparan?" Kata ibu memecah keheningan di meja makan itu. "Jatuh itu lama-lama bibir kalian," sindir ibu sambil melirik dan tersenyum ke arah Utari.
Laras menghela napas, lalu bergerak mengambil makanan dan bertingkah seolah-olah ia tidak ada apa-apa. "Iya, ini aku makan."
"Utami? Kamu nggak mau makan?" Tanya ibu sekali lagi, namun gadis itu hanya menggelengkan kepalanya.
Advertisement
Ibu menyentuh kepala anak bungsunya itu, "ono opo?" Digerak-gerakkannya kepala Utami sampai ia terlihat merasa terganggu. "Nggak pa-pa, bu. Aku cuma lagi capek aja. Tadi Mas Robi marah sama aku pas lagi latihan. Katanya aku latihannya kurang serius. Padahal ibu tahu sendiri, kan, aku selalu datang ke sanggar setiap hari. Aku nggak pernah merasa terpaksa kalau latihan tari."
"Mas Robi? Kayaknya mbak baru dengar nama itu, Tam." Tanya Utari sambil menciduk nasi ke dalam piringnya.
"Pelatih tari aku yang baru, mbak. Mbak Ratih kemarin resign karena harus pindah ke Jepang. Katanya diminta mengajar tari tradisional di Sekolah Indonesia-Jepang di sana." Jelas Utami. "Teman-temanku juga nggak ada yang suka sama dia karena cara mengajarnya terlalu keras dan kurang bersahabat. Intimidatif sekali, deh, mbak."
"Mbak Ratih juga bukannya galak?" Tanya ibu.
"Iya, bu. Tapi, Mas Robi ini beda. Aku juga nggak mengerti kenapa pihak sanggar mau menerima dia sebagai guru tari di sana. Aku bukannya mau menghina fisik seseorang ya, bu. Tapi, menurut Tami seorang guru tari sebaiknya tidak hanya mengajarkan gerakan badan, tapi juga gerakan wajah—ekspresi."
"Memangnya Mas Robi itu kena Mobius Syndrome atau bagaimana, Tam?"
"Bukan, mbak. Sebagian wajahnya hancur. Seperti terkena air keras atau terbakar. Yang pasti, banyak teman-temanku yang melihat wajah Mas Robi dengan tatapan jijik. Aku awalnya juga seperti itu, tapi setelah melihat cara dia menari, aku justru merasa kagum. Rasanya aku baru melihat ada laki-laki yang bisa begitu gemulai menarikan tarian perempuan. Gerakannya itu halus sekali, mbak. Malah menurutku hampir sempurna. Ya, pada saat itu ia menari topeng. Jadi, kami tidak harus melihat wajahnya yang rusak."
Utari lalu membayangkan sosok Mas Robi seperti yang diceritakan oleh Utami. Laki-laki bertubuh kurus semampai, seperti tubuh perempuan menari dengan mengenakan kain dan selendang. Berlenggak-lenggok dan gerakan tangan dan jari yang mengukel sempurna membuat siapapun yang memandangnya. Ia mencoba membayangkan adegan ketika Mas Robi membuka topeng dan menyunggingkan senyum dengan bibirnya yang bergincu merah cabai. Tapi, ia tidak benar-benar bisa membayangkan wajahnya yang rusak itu.
"Hhh... satu per satu temanku memutuskan untuk pindah sanggar. Nggak tahu, deh, aku bisa bertahan berapa lama. Masih banyak sanggar lain yang lebih bagus." Utami menghela napas. Sepertinya ia sudah cukup dengan uneg-uneg-nya. Ia mulai membalikkan piring yang ada di depannya dan menciduk nasi dari bakul.
Ibu melirik Utari lalu tersenyum, lalu berkata, "Kalau kamu ada masalah apa, Laras? Coba dibagi biar enteng."
Laras mengambil napas panjang dan tidak langsung berbicara. Pemandangan itu membuat suasana di meja makan menjadi sedikit tegang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Laras saat itu, semua mata menatap penasaran ke arah Laras. Ibu, Utari, dan Utami jadi ikut mematung sambil menunggu apa yang hendak dikatakan oleh Laras. Utari melihat ke arah ibu, mengangkat alisnya dan dibalas dengan gelengan kepala dari ibu. Tak lama kemudian, Laras mengambil napas panjang lagi.
Lalu, dengan suara keras dan cepat, ia berkata, "Ibu, aku ingin menikah dengan Ridwan."
Utari tersedak dan langsung mengambil segelas air yang ada di hadapannya. Ia tahu, baik ibu dan Utami pasti sedang melirik ke arahnya untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Namun, mereka juga tidak berniat untuk bertindak lebih dari itu.
"Mbak Utari, sungguh rasanya aku ingin mengucapkan beribu kata maaf kepada mbak. Tapi, kali ini aku mohon izinkan aku untuk menikah dengan Ridwan."
Utari tak mengalihkan pandangannya ke arah Laras. Ia sebenernya justru tidak mengharapkan sedikitpun permintaan maaf dari Laras atau dari siapapun karena tidak ada hal yang salah dengan keinginan untuk menikah. Permintaan maaf itu justru membuatnya merasa bersalah. Sejujurnya, ia juga tidak menyangka akan mendengarkan permintaan seperti itu untuk kedua kalinya dari mulut adik-adiknya. Ya, ia sudah pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Situasi yang entah bagaimana selalu menyeretnya dalam perasaan yang melelahkan hingga ia ingin segera lenyap dari pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama di hadapan ibunya.
"Laras, coba kamu bicara pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba menyampaikan keinginan untuk menikah dengan Ridwan? Apa kamu sudah yakin betul?" Tanya ibu sambil memegang ujung-ujung sendok dan garpunya. Pandangannya melayang turun ke bawah seraya mengambil sepotong daging ke dalam piringnya.
"Sudah lebih dari yakin, bu. Tak ada hal lain yang aku harapkan, selain menikah dengan Ridwan." Kata Laras mantap.
"Bagus kalau kamu sudah yakin. Kapan-kapan suruh Nak Ridwan datang kemari untuk membicarakan hal ini dengan ibu. Tidak usah buru-buru, yang penting sudah ada niat untuk melamar kamu dan menunjukkan keseriusannya saja ibu sudah senang. Pasti ibu restui." Kata ibu santai, sedikit mencairkan balok es yang menggelayut di dada Utari.
"Bukan begitu, bu." Kata Laras. Matanya yang berbentuk seperti mata kucing, entah mengapa, terlihat lebih tajam dari biasanya meskipun agak terlahang oleh poni yang menutupi seluruh dahinya. Utari memperhatikan bibir adiknya itu, yang menunjukkan getaran yang sangat halus. "Kalau bisa... Eh, bukan. Kami harus menikah sebelum akhir tahun ini, bu."
"Harus?" Ulang ibu.
"Iya. Harus." Jawab Laras mantap.
Kepala Utari terasa sakit seketika. Seperti ada yang menjalar dari belakang kepalanya ke mata sebelah kanannya. Alih-alih memegang kepala karena pusing, ia justru memegangi mata kanannya. Apa lagi ini? Batin Utari. Tangannya tiba-tiba gemetar, ia tiba-tiba merasa seperti meriang. "Bu, aku pusing. Ingin rebahan sebentar." Utari beranjak dari meja makan menuju kamarnya. Ia tahu yang ia lakukan ini jelas akan membuat Laras merasa bersalah dan menunjukkan kalau Utari memang benar-benar bermasalah dengan topik yang barusan disampaikan oleh adiknya. Sumpah mati serangan migraine yang melandanya ini benar-benar memaksanya untuk beristirahat sejenak. Tapi, saat itu Utari tidak sanggup untuk menjelaskan panjang lebar. Lagipula, gejala seperti ini memang sering muncul ketika ia sedang stress. Mungkin juga sebenarnya ia hanya sedang mengalami psikosomatis. Sangat mungkin.
Kamar Utari hanya berjarak beberapa meter dari meja makan. Walaupun ia sedang rebahan di atas tempat tidurnya, ia masih dapat mendengar percakapan Laras dan ibu yang membahas tentang keinginan Laras untuk menikah. Utami diam saja, setidaknya itu yang ditangkap oleh Utari. Ia memejamkan matanya, tidak berniat untuk tidur, tetapi untuk menajamkan indera pendengarannya hingga ia bisa mendengar suara denting piring yang beradu dengan sendok dan garpu dan suara sepoi angin yang masuk dari jendela kamarnya.
"Laras, apa maksud kamu, sih? Kenapa begitu memaksa ingin menikah akhir tahun ini?" kata ibu dengan nada suaranya yang terdengar seperti sedang khawatir.
"Kenapa, bu? Jeda satu tahun itu bukan waktu yang singkat, kan. Rasanya tidak berlebihan kalau aku menyiapkan segalanya selama setahun sebelum melaksanakan acara pernikahan. Lagipula, bu... aku tidak mengharapkan upacara pernikahan yang mewah, kok. Cukup mengundang keluarga dari kedua belah pihak. Akad nikah dan resepsi di rumah ini juga jadi. Bahkan, kalau ibu tetap keberatan, aku rela menikah di KUA tanpa ada seremonial apa pun, tanpa ada resepsi apa pun." Jelas Utari diplomatis yang justru membuat ibu semakin curiga.
"Bukan itu jawaban yang ibu harapkan. Dalam keadaan normal, satu tahun mungkin cukup untuk melaksanakan sebuah upacara pernikahan. Nggak perlu satu tahun, lusa pun kamu bisa menikah dengan Ridwan. Kamu sudah cukup umur dan ibu juga sudah sreg dengan Nak Ridwan—sepertinya dia baik. Tapi, kamu tahu kan situasinya seperti apa." Tidak terdengar suara siapapun. Hening sesaat. "Situasinya sekarang tidak semudah itu, Laras. Kamu harus mengeti itu."
Kedua perempuan itu tahu kemana arah pembicaraan itu bermuara. Raut wajah ibu berubah khawatir. Laras dapat merasakan dilema yang sedang dialami oleh ibunya.
"Bu, aku yakin kok Mbak Utari nggak akan keberatan. Dia hanya nggak enak sama ibu, takut kualat kalau melawan orang tua." Laras mengecilkan suaranya sedikit meskipun Utari masih dapat mendengarnya samar-samar. Utari tidak mengerti mengapa adiknya bisa bicara hal seperti itu di depan ibu. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Laras itu tidak sepenuhnya salah.
"Ndak... Pokoknya ibu nggak setuju kalau kamu menikah duluan daripada mbakyu-mu. Apa kata orang-orang melihat mbakmu sampai 'dilangkahi' dua kali oleh adiknya. Kamu nggak kasihan?"
Kata-kata ibu itu terdengar dengan jelas di telinga Utari. Ia mendengus kesal.
Mata sebelah kanan Utari terasa panas. Rasa sakit yang menjalar dari belakang kepalanya ke mata kanannya semakin terasa dan membuatnya ingin meringkuk. Saat itu, ia ingin sekali berlari kesana dan bilang kepada ibunya kalau tak ada yang perlu dikasihani. Sejak dulu Utari selalu merasa kalau apa yang dilakukan orang lain untuknya sebenarnya bukanlah semata-mata untuk kepentingan dirinya. Utari ingin sekali berkata pada Laras kalau ia boleh menikah dengan Ridwan kapanpun ia mau, tanpa harus mengkhawatirkan dirinya. Utari ingin ibu tahu kalau terkadang keinginannya untuk menikah dan menjadi istri seorang laki-laki telah sirna.
"Yah, kecuali kakakmu mau diruwat." Kata ibu belakangan.
Utari tak yakin apakah yang didengarnya itu benar atau tidak. Lagipula, ia tidak mengerti makna kata itu, "diruwat". Tidak lama setelahnya, Utari tertidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya itu ia sedang duduk di sebuah ruangan sempit yang gelap. Ruangan itu, hanya diterangi oleh lampu duduk berwarna kuning. Utari sedang duduk di depan lampu itu sambil memegang buku catatan kecilnya yang berwarna merah marun. Sepertinya, ia hendak menuliskan satu nama lagi di buku itu, namun daftar nama yang ada di dalamnya sudah semakin panjang. Utari terus membuka lembar demi lembar buku itu, hampir seluruh halamannya telah terisi, lantas ia bingung. Napasnya tersengal, seperti sedang kelelahan setelah mencari sesuatu yang tak kunjung ia temukan.
Advertisement
- In Serial315 Chapters

The Complete Alchemyst book 1
You've heard of superheroes, seen them flying across the sky, destroying great swaths of cities and ending countless innocent lives in order to defeat great evils and world-spanning threats and sell lots of sponsorships and merchandising opportunities. This is a story about the guy that is not those heroes. A supervillain in a world where making the right friends and political contacts is what separates the good guys from the bad. The Alchemyst is a story about a normal guy in a crazy world that spends his time trying to follow his dreams and conscience, working on new potions, thinking about girls, and lifting heavy shit, while trying to stay under the radar of the superheroes, supervillains, and governments that want what he can do. And occasionally turning them into makeshift melee weapons. If you enjoy The Boys, the Aberrant roleplaying game, Mystery Men, Trashy romances, Arnold Schwarzenegger movies, or SAW you may enjoy this book. Please note that this book has extremely graphic and sometimes gross fight scenes, heroes as villains, villains as heroes, opinionated and often politically incorrect characters, some graphic sex scenes, dad jokes, dirty jokes, realistic depictions of romance and flirting, bondage and dominance themes, and more than a few cuss words when they are really appropriate. This is NOT a superhero genre deconstruction. Many heroes truly are heroes, and they don't all need to be destroyed to make a good story, but it does look into the dark side of superpowers and the unreasonable and often contradictory demands placed on exceptional people.
8 205 - In Serial72 Chapters

Game On
Matthew Barnett tried to warn those around him -- the Game was going to start soon. Everyone was going to suffer and most were going to die, unless they took some serious steps to prepare themselves for what was to come. Diagnosed with Schizophrenia, he was hospitalized for several months until the proper medications could be found to help him control his inability to distinguish reality from fantasy and could return back to a normal school life.But...What if it was the world which was actually insane, and not him? What if he was right? What if it really was time for everyone to get their "Game On"?Warning: Rated M[18+] for language, sexual themes, gore, violence, adult situations, and too much awesomeness.
8 129 - In Serial50 Chapters

Legion, God of Monsters
An epic fantasy adventure inspired by elements of GameLit and Isekai. Legion, God of Monsters follows a new god and his inhuman prophet as they begin to turn the world of Hanulfall upside down. From adventurers, nobles, and politicking goblins to beastkin, orcs, trolls, and many other fantastical races, they find themselves embroiled in the scheming of kingdoms and the fate of a tribe.
8 192 - In Serial28 Chapters

Legend of the Guild: Point Blank
Status: On hiatus indefinitely, because I'm going to be busy and the story is now at a place where it needs major reconstruction. Curt is a young gunslinger from a small town called Ore Town, situated in a barren wasteland known as the Dusts. While sabotaging the gang threatening his town, Curt is forced to take a leap of faith, literally. He plunges into the sea of clouds expecting death, only to arrive in an entirely new world beneath his own. Saved by a young girl using magic, Curt isn't too sure what to make of his second chance of life. When he meets a fellow Duster who had fallen years ago, he's roped into becoming second-in-command of a brand new guild. Guild duties aren't easy, especially as Curt is tasked to recruit fighters to take on the Grand Guild Tournament, where the winning guild takes home an enormous prize pool -- and most importantly, a mysterious ticket to the fabled "Star City" that exists above the clouds. Going with the flow only takes him so far, and Curt soon finds himself burdened with more responsibility than he bargained for, including the fate of the two worlds. ==============================Wordpress This webnovel is written for fun, and everything posted is essentially a first draft. Beware of typos and lack of creative descriptions — my main priority is to get the story out over writing quality. Still, I hope you enjoy the story. Updates are sporadic, but I aim to release a chapter (~2000-3000 words) at least once a week. Average release time is 1 chapter/3 days. I took inspiration from the lore of the MMO, Dungeon Fighter Online (Dungeon & Fighter), and there may be easter eggs or references to the game, but the story and characters have become wholly original and standalone. [Note: Profanity tag is up because profanity is present, but infrequent]
8 139 - In Serial11 Chapters

My Angel
Rosalie Hale. Forks High's ice queen.Hayden Taylor. New girl.Not exactly Romeo and Juliet.
8 55 - In Serial43 Chapters

BRUINS 3
Welcome to the most dangerous trilogy of women's soccer. (3/3)
8 190







 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl